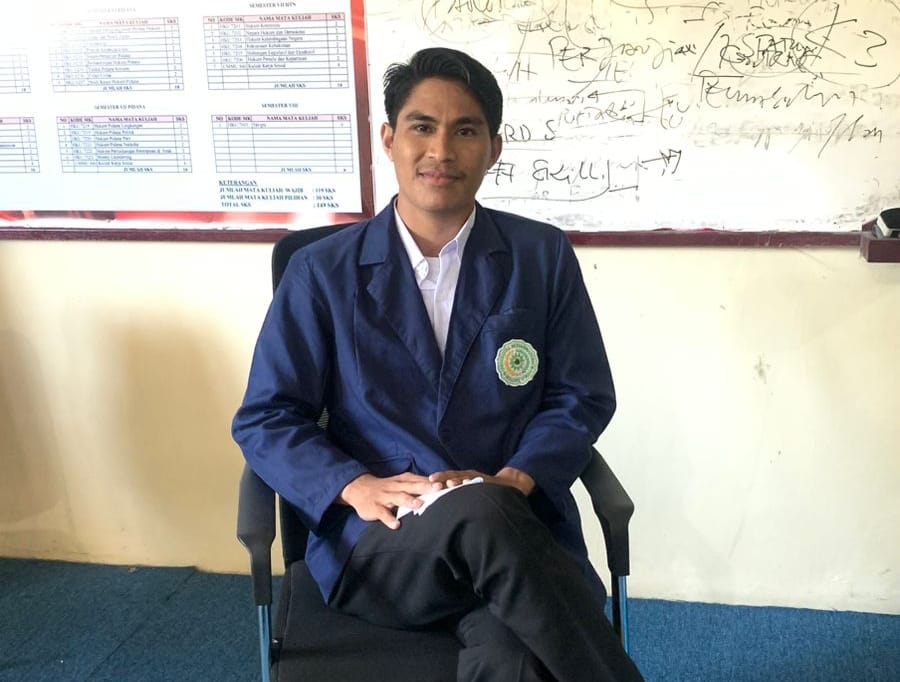Oleh: Ardi Turege
Ketua UKM, Law Debate And Research Study (LDRS) FH UMMU
___________________
DALAM kehidupan bernegara, hukum dan kekuasaan merupakan dua elemen fundamental yang saling berinteraksi. Hukum bertujuan menciptakan keadilan dan keteraturan, sementara kekuasaan digunakan untuk menjalankan dan menegakkan hukum itu sendiri.
Namun, dalam praktiknya, sering terjadi dilema ketika kekuasaan tidak digunakan untuk menegakkan hukum secara adil, melainkan untuk kepentingan tertentu. Dilema ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum mengontrol kekuasaan, ataukah kekuasaan justru yang membentuk dan mengontrol hukum?
Dalam teori ideal, hukum adalah panglima. Ia menjadi penuntun moral, sosial, dan politik dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum seharusnya berdiri di atas segala bentuk kekuasaan bukan di bawah kekuasaan. Namun dalam praktiknya, relasi antara hukum dan kekuasaan seringkali menyisakan dilema yang kompleks dan ironis. idealnya, kekuasaan harus tunduk pada hukum. Konsep ini dikenal sebagai “rule of law” atau “supremasi hukum”, yaitu prinsip bahwa setiap orang, termasuk pejabat negara, berada di bawah hukum dan tidak ada yang kebal terhadapnya.
Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan, memberikan kepastian dan kemanfaatan, melindungi hak asasi, serta mengatur ketertiban sosial. Akan tetapi, ketika kekuasaan terlalu dominan, hukum kerap kali kehilangan independensinya sebagai panglima. Ia dibengkokkan, ditafsirkan sepihak, atau bahkan dimanipulasi demi mempertahankan kekuasaan segelintir orang-orang munafik yang bertopeng dibalik wajah kekuasaan (ebaus of power).
Sejarah mencatat banyak contoh di mana hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan. Dari rezim otoriter yang memenjarakan lawan politik dengan dalih hukum, hingga pemerintahan demokratis yang menggunakan celah hukum untuk memperpanjang masa jabatan atau mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Di titik inilah muncul dilema besar: apakah hukum benar-benar berdiri sendiri, atau hanya menjadi bayang-bayang kekuasaan?
Pada prinsipnya; Kekuasaan seharusnya tunduk pada hukum. Namun realitas di negara ini, meskipun negara ini termasuk negara yang menganut sistem demokrasi sekalipun, menunjukkan bahwa kekuasaan justru seringkali memegang kendali atas proses hukum (do proses of law).
Terjadinya, intervensi politik terhadap lembaga peradilan, pemilihan hakim yang berpihak, hingga tekanan terhadap aparat penegak hukum: kepolisian, adalah bentuk distorsi relasi hukum dan kekuasaan. Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan dibutuhkan untuk menjalankan hukum. Tanpa kekuasaan, hukum menjadi tak lebih dari teks mati di atas kertas bagaikan jasad yang tidak bernyawa, pada hakikatnya hukum dan kekuasaan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Maka, relasi antara hukum dan kekuasaan semestinya bersifat simbiosis: kekuasaan diberi mandat oleh hukum, dan hukum ditegakkan oleh kekuasaan yang sah.
Hukum dan kekuasaan seharusnya berjalan beriringan dalam menciptakan keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat. Hukum adalah aturan yang mengikat semua orang tanpa terkecuali, sedangkan kekuasaan adalah alat untuk menegakkan hukum tersebut. Namun dalam kenyataannya, hubungan antara hukum dan kekuasaan seringkali tidak seimbang dan menimbulkan dilema yang kompleks.
Di satu sisi, hukum idealnya menjadi panglima tertinggi yang mengarahkan bagaimana kekuasaan dijalankan. Kekuasaan harus tunduk pada hukum agar tidak disalahgunakan. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan justru sering kali mempengaruhi hukum, bahkan sampai mengendalikannya. Hukum bisa dijadikan alat politik untuk membungkam lawan, melindungi kepentingan penguasa, atau melanggengkan kekuasaan. Seperti apa yang dikatakana oleh Lord Acton ”power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely“, Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut korup secara absolut. Oleh karena itu kekuasaan perlu dibatasi agar berjalan tepat di jalur yang tepat.
Dilema muncul ketika hukum tidak lagi berdiri di atas kekuasaan, melainkan berada di bawah kendalinya. Ini berbahaya, karena hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung keadilan dan pemberi kepastian dan kemanfaatan. Masyarakat menjadi tidak percaya lagi pada sistem hukum, dan ketidakadilan menjadi hal yang dianggap biasa.
Dalam konsep negara hukum (Rechtsstaat), hukum berada di atas kekuasaan. Negara hanya boleh bertindak jika ada dasar hukum (legalitas). Teori ini menegaskan pentingnya supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
“”Namun di sisi lain, hukum tanpa kekuasaan juga tak berdaya. Sebaik apapun aturan yang dibuat, tanpa adanya kekuasaan untuk menegakkannya, hukum hanya menjadi tulisan tanpa makna”.
Bertolak belakang dengan Rechtsstaat, Machtsstaat adalah konsep di mana kekuasaan merupakan elemen dominan dalam pemerintahan. Negara bertindak berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya, bukan hukum. Ini sering digunakan untuk melegitimasi tindakan otoriter.
Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum dan kekuasaan. Kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, dan hukum harus ditegakkan oleh kekuasaan yang adil dan bertanggung jawab. Tanpa keseimbangan ini, yang lahir bukan keadilan, tapi ketidakpastian, ketakutan, dan penyalahgunaan wewenang (ebaus of power).
Hukum dan kekuasaan adalah dua pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, menjamin keadilan, dan menjaga ketertiban. Sementara itu, kekuasaan adalah alat atau wewenang yang digunakan untuk menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam konsep negara hukum, kekuasaan harus tunduk pada hukum. Namun pada kenyataannya, relasi antara keduanya tidak selalu berjalan harmonis. Inilah yang menimbulkan dilema yang kompleks antara hukum dan kekuasaan.
Salah satu bentuk dilema yang sering terjadi adalah ketika kekuasaan justru mengendalikan hukum. Dalam kondisi seperti ini, hukum tidak lagi berdiri netral dan adil sebagaimana yang diagung-agungkan dalam prinsip (equality before the law), melainkan menjadi alat bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Hukum dipolitisasi, digunakan untuk menghukum lawan politik, atau melindungi kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, hukum kehilangan wibawanya dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pun menurun dan terjadi degradasi kepercayaan yang berkepanjangan.
Kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum cenderung melahirkan penyalahgunaan wewenang. Dalam sejarah, banyak pemimpin yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri, menindas rakyat, dan mengabaikan prinsip keadilan. Tanpa kontrol hukum yang kuat, kekuasaan bisa berubah menjadi tirani.
Namun, di sisi lain, hukum yang tidak didukung oleh kekuasaan juga tidak akan efektif. Hukum memerlukan kekuasaan untuk dapat ditegakkan. Aturan yang baik tidak akan berguna jika tidak ada institusi yang memiliki wewenang dan keberanian untuk menegakkannya. Oleh karena itu, kekuasaan sebenarnya dibutuhkan untuk membuat hukum berjalan.
Mencari Titik Keseimbangan
Dilema antara hukum dan kekuasaan hanya bisa diatasi jika keduanya saling menguatkan dalam kerangka yang benar. Kekuasaan harus tunduk pada hukum, dan hukum harus memiliki kekuatan untuk menundukkan kekuasaan yang melenceng. Dalam sistem demokrasi, keseimbangan ini dijaga melalui prinsip checks and balances, di mana setiap lembaga negara memiliki fungsi pengawasan satu sama lain.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ini. Kesadaran hukum, kebebasan berpendapat, dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik dapat menjadi kekuatan penyeimbang antara hukum dan kekuasaan.
Dilema antara hukum dan kekuasaan akan selalu ada selama manusia hidup dalam sistem sosial dan politik. Namun, selama prinsip keadilan ditegakkan dan kekuasaan tidak dibiarkan lepas dari kendali hukum, maka hukum akan tetap menjadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan.
Negara yang kuat bukanlah negara dengan penguasa yang berkuasa tanpa batas, tetapi negara yang hukum dan kekuasaannya berjalan seimbang demi keadilan bagi seluruh rakyatnya.
Karena pada Prinsipnya, Negara Hukum Indonesia mempunyai prinsip: Supremasi hukum (the rule of law): Pemerintahan harus tunduk pada hukum, bukan pada figur manusia. Adanya Pembatasan kekuasaan: Kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, termasuk hak asasi manusia. Kemudian prinsip Peradilan yang bebas: Lembaga peradilan harus independen agar dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dan menjaga jalannya demokrasi. Perlindungan HAM dan keadilan sosial: Negara menjamin hak asasi manusia dan menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Maka untuk menjaga keseimbangan antara hukum dan kekuasaan dalam negara ini oleh Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan supremasi konstitusi sebagai pembatas kekuasaan negara dan dasar bagi terwujudnya negara hukum Indonesia. Menurutnya, konstitusi mengatur pemerintahan dan mengatur rakyat, sehingga kekuasaan tanpa kewenangan konstitusional adalah kekuasaan tanpa dasar. Ia juga menekankan pentingnya prinsip “the rule of law, not of man” untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menggarisbawahi perlunya institusi penyeimbang seperti kekuasaan kehakiman yang independen untuk menjaga checks and balances dalam sistem pemerintahan.
Solusi atas dilema ini bukanlah memisahkan hukum dari kekuasaan secara mutlak, tetapi menegakkan prinsip checks and balances yang kuat. Lembaga peradilan harus independen, media harus bebas mengkritik, dan masyarakat sipil harus aktif mengawasi melalui gerakan demonstran sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Penegakan hukum tidak boleh dipolitisasi, dan kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi serta prinsip etika.
Jika kekuasaan tak lagi tunduk pada hukum, maka hukum kehilangan maknanya. Sebaliknya, jika hukum tak diberi kekuasaan untuk bertindak, maka keadilan menjadi ilusi. Keseimbangan itulah yang harus terus diperjuangkan oleh semua elemen bangsa. (*)