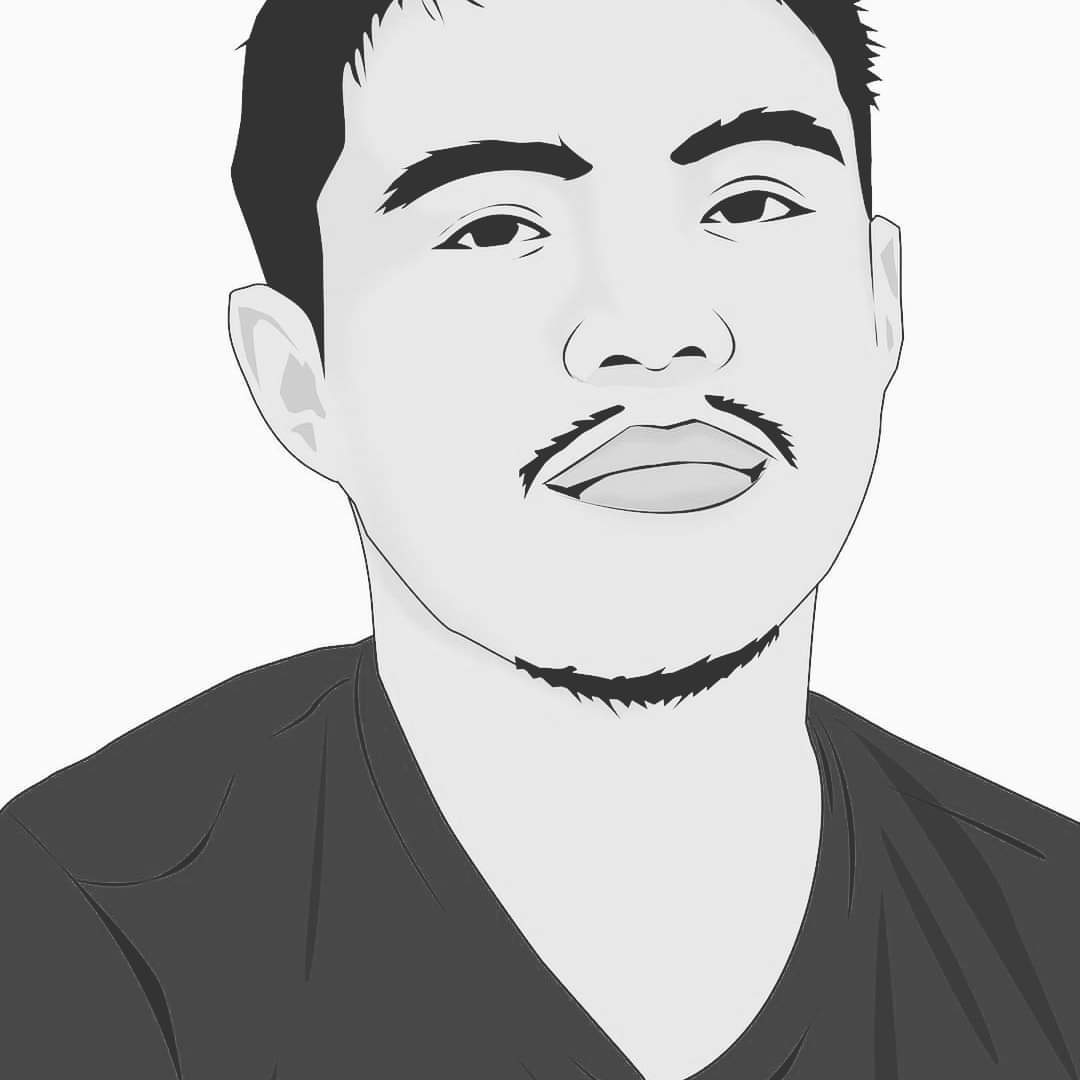Oleh: Ali Akbar Djaguna
Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Morotai
_______________
“Kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, kita meminjamnya dari anak cucu kita.” — Chief Seattle, Pemimpin Suku Duwamish (1854)
KUTIPAN mendalam dari Chief Seattle ini mengandung pesan moral yang amat relevan di masa kini, ketika manusia sering kali tergoda untuk mengejar kemakmuran jangka pendek dengan mengorbankan keseimbangan bumi. Kalimat sederhana ini menyiratkan tanggung jawab besar bahwa apa yang kita miliki hari ini—tanah, air, udara, hutan, dan laut—bukan milik pribadi atau generasi saat ini, melainkan titipan yang harus dijaga dengan kesadaran penuh demi masa depan anak cucu. Prinsip ini menjadi dasar bagi negara-negara yang berhasil mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Salah satu di antaranya adalah Islandia Baru, sebuah negara kepulauan yang dikenal karena keberhasilannya menjaga keseimbangan antara industri tambang dan pariwisata tanpa merusak harmoni alam.
Islandia Baru bukan sekadar tanah yang dikelilingi samudra dan gunung berapi yang aktif. Ia adalah cermin bagaimana negara kecil bisa menjadi besar karena kebijakan yang bijak dan kesadaran ekologis yang tinggi. Pemerintah dan masyarakatnya memiliki pemahaman mendalam bahwa alam adalah fondasi kehidupan. Mereka menolak paradigma lama yang menempatkan pertambangan sebagai pusat ekonomi yang merusak. Sebaliknya, mereka menempatkan alam sebagai mitra pembangunan. Segala bentuk eksploitasi sumber daya alam, termasuk tambang, diatur dengan standar lingkungan yang sangat ketat. Prinsip “zero waste mining” diterapkan dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap material hasil tambang dimanfaatkan secara efisien, limbah diolah kembali, dan area bekas tambang direhabilitasi agar kembali hijau dan hidup.
Namun keberhasilan Islandia Baru tidak berhenti pada tata kelola tambangnya. Mereka melangkah lebih jauh dengan membangun industri pariwisata yang berkelanjutan. Keindahan alamnya dijaga bukan untuk dijual habis-habisan, tetapi untuk dirayakan dan diwariskan. Pemerintah menanamkan prinsip eco–tourism, pariwisata yang ramah lingkungan dan berakar pada kesadaran konservasi. Setiap kawasan wisata memiliki batas kunjungan untuk menjaga daya dukung alam. Wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati pemandangan, tetapi juga untuk belajar bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan alam. Masyarakat lokal menjadi garda terdepan: mereka dilatih, diberdayakan, dan diikutsertakan dalam mengelola pariwisata berbasis komunitas. Dengan begitu, pariwisata menjadi sarana peningkatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar komersialisasi alam.
Jika pandangan dialihkan ke bagian timur Indonesia, Pulau Morotai tengah berada di titik penting dalam perjalanannya. Pulau ini, yang dikenal sebagai “mutiara di bibir Pasifik”, memiliki potensi alam luar biasa. Lautnya kaya akan ikan, pantainya memukau, sejarahnya monumental, dan di bawah tanahnya tersimpan pasir besi berkualitas tinggi. Dua sektor besar—pertambangan dan pariwisata—menjadi daya tarik sekaligus tantangan bagi masa depan Morotai. Di satu sisi, tambang menjanjikan peningkatan pendapatan daerah dan lapangan kerja. Namun di sisi lain, pariwisata menjanjikan keberlanjutan, identitas, dan masa depan ekonomi yang lebih ramah terhadap lingkungan.
Inilah titik di mana Morotai bisa belajar dari Islandia Baru. Pengalaman Islandia Baru menunjukkan bahwa kemajuan tidak harus berarti eksploitasi besar-besaran. Justru kemajuan sejati lahir dari kemampuan menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi, antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian alam. Islandia Baru mengajarkan bahwa tambang bisa berjalan selama ada kontrol yang kuat, transparansi publik, dan tanggung jawab lingkungan yang nyata. Setiap perusahaan tambang wajib melibatkan masyarakat lokal, menyusun laporan terbuka tentang dampak lingkungan, dan berkomitmen pada pemulihan pasca tambang.
Prinsip ini bisa diadopsi oleh Morotai agar tidak terjebak dalam pola lama pembangunan yang eksploitatif. Pemerintah daerah perlu membangun tata kelola berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat. Masyarakat lokal, terutama nelayan, petani, dan pemuda, harus menjadi bagian dari proses perencanaan, bukan sekadar penonton dari kebijakan yang datang dari luar. Dengan cara itu, pembangunan tambang bisa berjalan beriringan dengan perlindungan ekosistem laut dan darat.
Pada saat yang sama, Morotai memiliki peluang besar untuk menjadikan pariwisata sebagai pilar utama ekonomi masa depan. Potensi wisata sejarah Perang Dunia II, pesona bahari, serta budaya lokal bisa diolah menjadi destinasi unggulan yang berkelas dunia. Namun semua itu hanya bisa tercapai jika alam dijaga dengan baik. Islandia Baru membuktikan bahwa wisata dan lingkungan adalah dua kekuatan yang saling menguatkan. Semakin lestari alamnya, semakin tinggi nilai pariwisatanya.
Kutipan Chief Seattle di awal tulisan ini bukan sekadar pengingat moral, tetapi juga arah bagi Morotai untuk menata langkah. Bahwa kekayaan alam tidak bisa dinikmati hanya sekali, melainkan harus dikelola agar terus memberi kehidupan dari generasi ke generasi. Dari Islandia Baru, Morotai bisa belajar bahwa pulau kecil pun dapat memiliki visi besar. Visi yang menempatkan keseimbangan sebagai inti pembangunan: menambang dengan hati, berwisata dengan kesadaran, dan hidup berdampingan dengan alam tanpa saling merusak.
Jika Islandia Baru mampu menjadi contoh dunia dengan kebijakan tambang berkelanjutan dan pariwisata hijau, maka Morotai pun bisa melangkah ke arah yang sama. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk belajar, kejujuran dalam mengambil keputusan, dan komitmen untuk menjaga bumi seperti menjaga kehidupan itu sendiri. Karena pada akhirnya, kemakmuran sejati bukanlah hasil dari seberapa banyak alam kita gali, tetapi seberapa bijak kita merawatnya. (*)