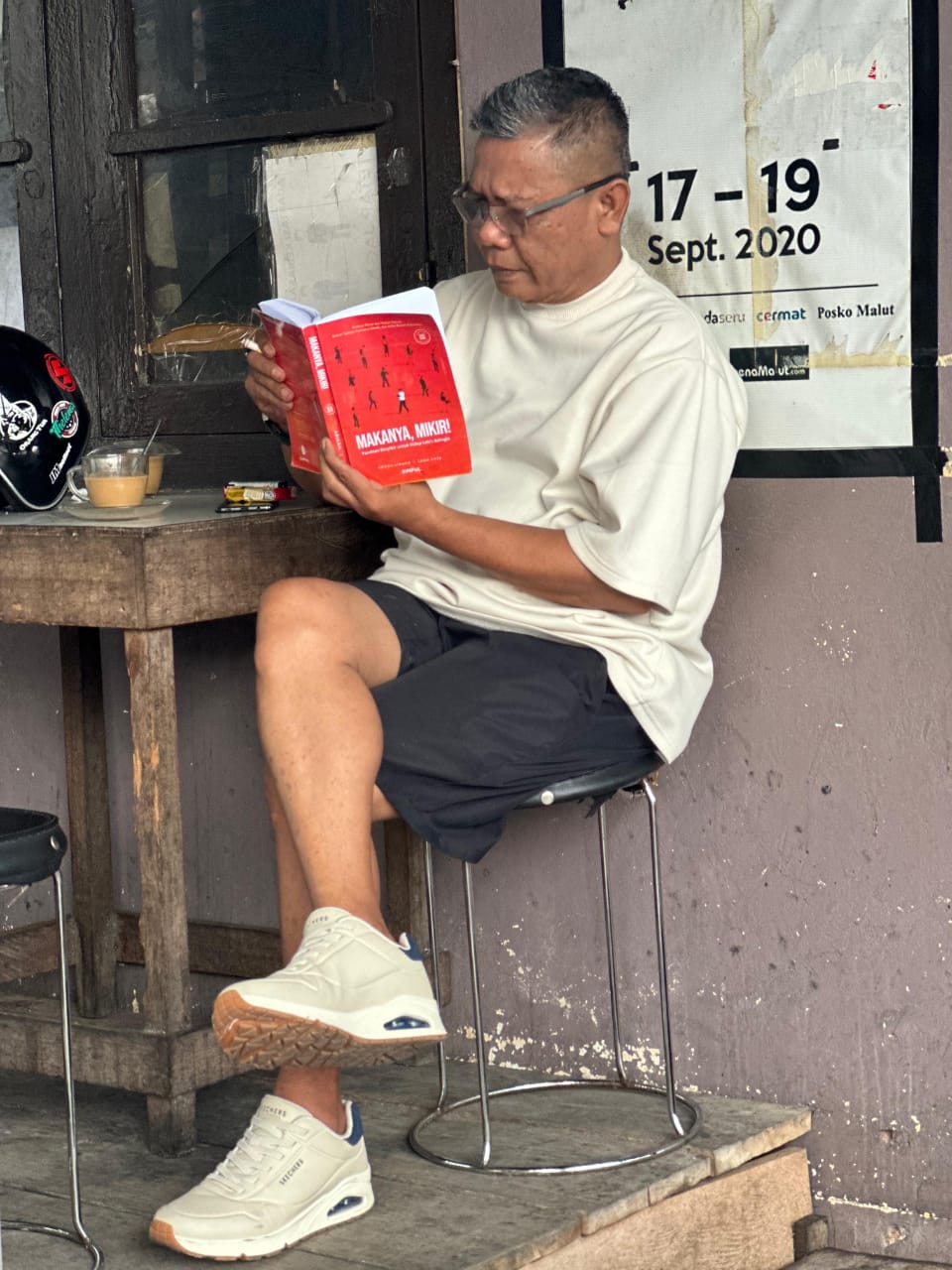Oleh: Syarif Tjan
Direktur TJAN Institute, Pengamat Sosial & Lingkungan
______________________
NAMA Tete Ali memang sedang viral, tapi bukan karena prestasi atau kebijaksanaan seperti layaknya seorang tetua. Tete Ali viral karena kondisi mentalnya yang membuatnya mudah terpancing emosi dan mengeluarkan makian. Puncaknya semalam setelah saya selesai menonton live di TikTok jumpa fans Tete Ali di Taman Tulang Ikan-Dufa Dufa Ternate, dengan tagline “The King of Emotional”.
Jujur, saya tidak bisa tidur. Ada yang mengganjal di hati saya melihat bagaimana seorang kakek 84 tahun dari Morotai dijadikan bahan tontonan ribuan orang. Bayangkan, setiap hari Tete Ali ini jalan-jalan tanpa tujuan sambil bawa tas, bergumam sendiri. Warga Morotai sudah tahu dia punya masalah mental. Tapi bukannya dikasihani atau ditolong, malah sering dijahilin supaya marah. Nah, kebiasaan buruk ini yang kemudian “diangkat” jadi konten digital.
Saya sempat mikir, kenapa ya kita bisa sampai segini? Kok bisa-bisanya kita ketawa liat penderitaan orang lain? Setiap konten yang dibuat temanya sama saja: bikin Tete Ali marah terus Tete Ali maki-maki, terus kita pada ketawa. Itu hiburan macam apa ?
Kalau mau jujur, ini sebenarnya bukan hal baru. Dulu-dulu juga ada yang namanya “Nadjib Alkatiri”, di mana Nadjib dengan talenta yang full humoris menampilkan tontonan yang menghibur masyarakat Ternate. Dengan kesadaran pengendalian emosi, Nadjib tampil dengan joke yang memang dari awal dia persiapkan untuk menghibur. Tanpa kursus stand up comedy, Nadjib membawa bakat alam sebagai pelawak lokal.
Bedanya sekarang cuma medianya aja – dari panggung komedi ke layar HP. Audiens-nya juga bukan cuma beberapa ratus orang, tapi ratusan ribu. Dan yang paling parah, kita merasa ini normal-normal aja. Waktu Tete Ali dibawa ke Ternate, saya shock lihat antusiasme masyarakatnya. Masyarakat berjubel hanya ingin melihat Tete Ali dari dekat. Semua berdesak–desakan ingin salaman dengan Tete Ali. Pokoknya rame sekali! Sampai bikin jadwal Temu Fans Tete Ali segala.
Serius? Ini bukan artis atau tokoh penting, ini kakek yang butuh bantuan medis. Tapi entah kenapa dia jadi objek eksotis yang menarik buat dilihat. Mungkin karena dia “beda” dari kita yang “normal”. Bagi orang antropologi, fenomena ini disebut “othering” – proses dimana kita nganggep orang yang berbeda sebagai objek fascinasi. Claude Lévi-Strauss pernah menjelaskan bagaimana masyarakat cenderung menempatkan individu yang dianggap “tidak normal” sebagai “liyan”, sesuatu yangg lain dan menarik buat diamati.
Tete Ali jadi eksotis justru karena perilakunya yang tidak sesuai norma sosial. Ironisnya, pengecualian inilah yang bikin dia jadi pusat perhatian. Yang bikin saya sedih, ini terjadi di Maluku Utara, dimana secara tradisi, orang tua dan yang punya keterbatasan itu selalu dijaga dan dihormati. Yang terjadi malah sebaliknya, dijadikan tontonan. Media sosial sepertinya sudah mengubah perilaku dan pola berfikir kita.
Terus yang bilang “Kan dia dapat duit dari donasi, jadi menguntungkan.” Astaga, logika macam apa itu? Memang Tete Ali dapat sumbangan, tapi dengan cara apa?
Dengan terus-terusan dipancing sampai stres dan marah-marah. Itu namanya bukan bantuan, tapi eksploitasi berkedok kemanusiaan. Kita kasih duit sedikit, terus merasa berhak menjadikan Tete Ali sebagai badut. Semakin kontroversial, semakin viral. Semakin viral, semakin banyak duit yang masuk. Kita tidak peduli apakah kontennya etis atau tidak. Yang penting angka view naik terus.
Saya jadi inget teori dari Pierre Bourdieu tentang konsep “kekerasan simbolik”, yaitu kekerasan yang tidak disadari korbannya karena dikemas dalam bentuk yang terlihat normal atau bahkan menguntungkan. Kondisi ini persis yang terjadi sama Tete Ali. Dia tidak sadar kalau lagi dieksploitasi karena dia dapat duit. Yang menuntun Tete Ali dalam konten juga tidak merasa melakukan kekerasan karena merasa “membantu.”
Terus ada lagi yang namanya dramaturgi sosial dari Erving Goffman. Biasanya orang itu sadar kalau lagi “perform” di depan publik, punya strategi bagaimana cara presentasi diri yang baik. Tapi Tete Ali? Dia tidak punya kesadaran itu. Tete Ali tidak tahu kalau lagi dijadikan bahan pertunjukan. Ini berbeda sekali sama influencer yang sengaja bikin persona buat dapetin followers dan duit.
Yang lebih menyedihkan lagi, banyak orang yang sebenarnya tidak nyaman sama perlakuan ini tapi memilih diam. Mereka ikut arus, karena mayoritas orang terlihat enjoy dan terhibur. Mereka tidak berani menyuarakan keberatan mereka. Padahal dalam lubuk hati mungkin mereka tahu ini salah.
Dalam sosiologi, fenomena ini disebut “spiral of silence“. Orang cenderung diam kalau merasa opininya beda dari mayoritas. Takut dikucilkan atau dianggep aneh. Padahal mungkin banyak yang sebenarnya tidak setuju, tapi karena tidak ada yang berani menyuarakan, jadinya keliatan sepertinya semua orang mendukung.
Melalui tulisan ini, saya mengajak kita pikir baik-baik. Sebagai manusia biasa, Tete Ali kebetulan punya masalah kesehatan mental. Dia butuh pengobatan dan dukungan, bukan dijadiin karakter hiburan. Identitas aslinya sebagai seorang kakek yang butuh pertolongan malah tenggelam sama image “penghibur” yang diciptakan buat konsumsi massa.
Guy Debord pernah bilang kita hidup dalam “society of the spectacle” – masyarakat yang realitasnya digantikan sama representasi spektakuler.
Tete Ali yang aslinya cuma kakek dengan gangguan mental, berubah jadi “produk hiburan” yang identitas aslinya hilang. Dia tidak lagi dilihat sebagai manusia yang butuh bantuan medis, tapi sebagai “konten” yang bisa menghasilkan views dan duit.
Dalam kondisi ini, bagaimana dampaknya buat Tete Ali sendiri? Meski mungkin dia tidak paham sepenuhnya apa yang terjadi, tapi dipancing terus-menerus buat marah pasti tidak baik buat kondisi mentalnya yang sudah rapuh. Dan sampai hari ini belum ada langkah-langkah pengobatan serta pendampingan medis untuk Tete Ali.
Yang bikin saya tambah kesal, ini terjadi karena kurangnya akses ke layanan sosial dan kesehatan mental di daerah seperti Morotai. Andaikan di awal Tete Ali sudah disentuh Dinas Sosial Morotai ataupun Provinsi Maluku Utata serta mendapat penanganan medis yang tepat, mungkin kondisinya tidak sampai seperti ini.
Fenomena Tete Ali sekaligus menjadi interupsi bagi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai agar berbenah dan responsif dalam melayani masyarakat.
Stigma terhadap penyakit mental di masyarakat kita juga masih kental. Orang dengan gangguan mental masih sering dilihat sebagai sesuatu yang aneh, lucu, bahkan menakutkan. Padahal ini kondisi medis yang butuh penanganan profesional, bukan bahan lelucon. Kita mundur secara peradaban.
Platform media sosial seharusnya juga ikut bertanggung jawab. Mereka punya power besar buat mengkurasi konten yang beredar. Tapi sayangnya, profit masih jadi prioritas utama dibanding etika dan kemanusiaan.
Ini yang Max Weber sebut sebagai “rasionalisasi” – semua dinilai dari efisiensi dan keuntungan. Tete Ali dianggap “efisien” sebagai konten karena bisa menghasilkan engagement tinggi dengan modal kecil. Nilai kemanusiaannya tereduksi jadi cuma angka-angka: berapa view, berapa like, berapa duit yang masuk. Sadis memang!
Saya juga berpikir, fenomena Tete Ali tidak cuma terjadi di Maluku Utara. Di mana-mana ada saja orang yang dieksploitasi buat konten viral. Format “prank” atau “roasting” yang populer di platform.
Jujur, ini bikin saya mikir keras tentang arah peradaban digital kita. Kita mau kayak apa sih ke depannya? Mau jadi masyarakat yang menganggap eksploitasi kerentanan sebagai hiburan yang wajar? Atau mau membangun ekosistem digital yang lebih humanis dan empatis?
Pertanyaan-pertanyaan ini sudah saatnya dijawab lewat program litetasi digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk wilayah Maluku Utara. Tetapi semuanya kembali ke jari-jari kita. Setiap kali kita klik, tonton, atau share konten, kita sebenarnya lagi memberi suara tentang jenis masyarakat yang kita inginkan. Saya harap kita bisa lebih bijak dalam memilih. Karena masa depan kemanusiaan kita bergantung pada pilihan-pilihan kecil namun berarti ini.
Kembali ke Tete Ali. Yang jelas, Tete Ali butuh perlindungan, perawatan medis yang layak, dan penghormatan atas martabatnya sebagai manusia. Bukan panggung digital buat menghibur kita yang merasa lebih “normal” dari dia. Kita semua manusia, dan setiap manusia berhak diperlakukan dengan bermartabat, terlepas dari kondisi fisik atau mentalnya.
Mungkin saatnya kita introspeksi diri. Apakah hiburan yang kita konsumsi sudah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kita anut? Atau kita masih terjebak dalam siklus konsumsi konten yang eksploitatif tanpa sadar?
Saya berharap, tulisan ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Bahwa di balik setiap konten viral, ada manusia dengan perasaan, martabat, dan hak untuk dihormati. Mari kita jadi konsumen digital yang lebih bertanggung jawab. (*)