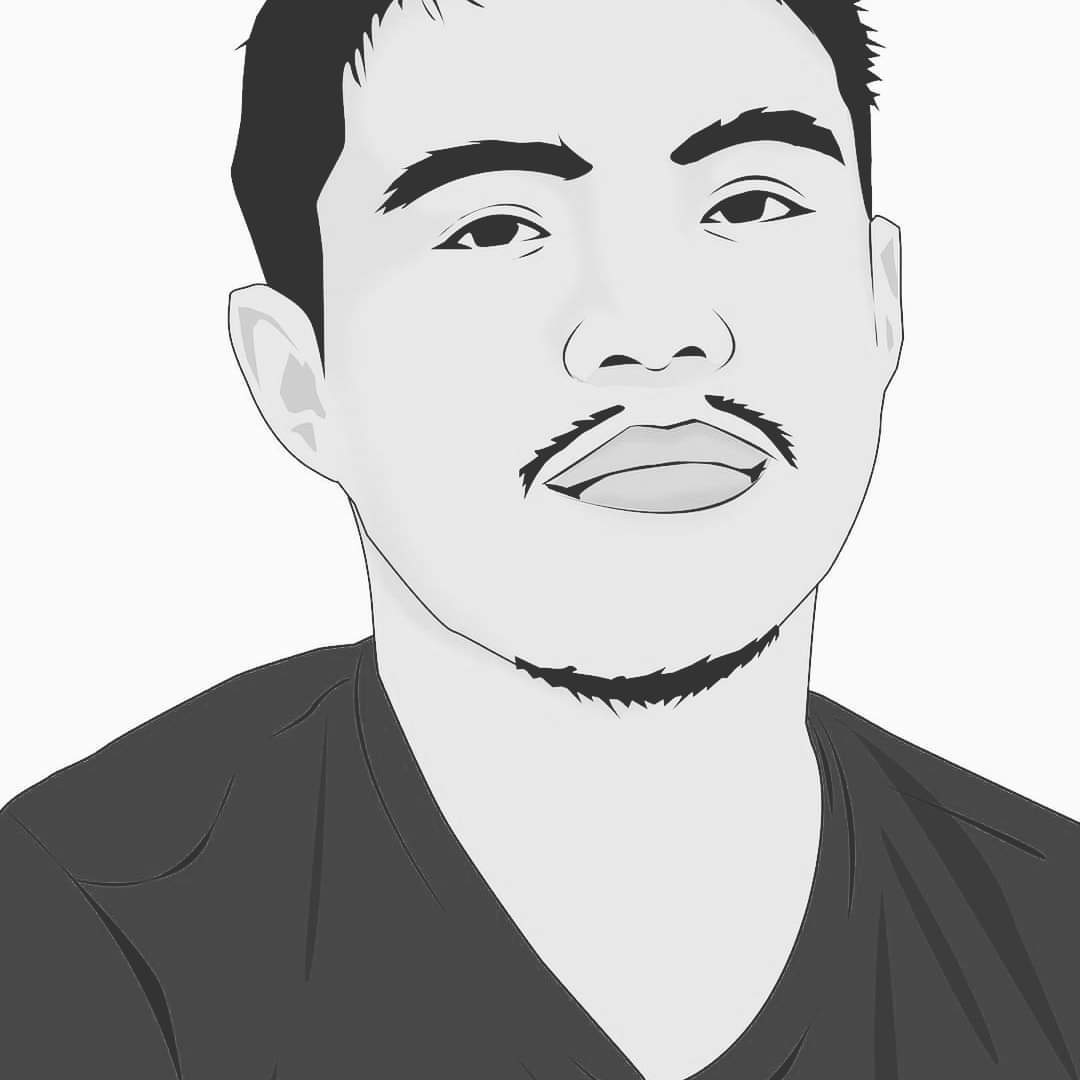Oleh: Ali Akbar Djaguna
Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Morotai
_____________
PERDEBATAN tentang masuknya tambang pasir besi di Pulau Morotai kembali mengemuka. Di satu sisi, muncul kekhawatiran akan ancaman kerusakan lingkungan dan terganggunya ekosistem pesisir. Namun di sisi lain, ada realitas ekonomi yang tak bisa diabaikan: lemahnya fiskal daerah dan kebutuhan mendesak untuk menumbuhkan sumber pendapatan baru. Morotai kini berada di tengah dilema yang sulit — antara menjaga lingkungan dan memperkuat fondasi keuangan daerah.
Fakta fiskal Morotai berbicara sendiri. Anggaran daerah setiap tahun sebagian besar bergantung pada dana transfer dari pusat. Sementara PAD yang dihasilkan secara lokal masih kecil dan cenderung stagnan. Ketika biaya pelayanan publik meningkat, sementara penerimaan terbatas, pemerintah daerah terjebak dalam ruang sempit untuk berinovasi. Dalam situasi seperti ini, sektor pertambangan sering dianggap sebagai pintu darurat — sumber pendapatan yang cepat dan nyata.
Namun, membahas tambang tidak bisa berhenti pada stigma kerusakan. Dunia telah berubah. Banyak daerah dan negara berhasil menjadikan sektor tambang sebagai sumber kekuatan fiskal sekaligus penggerak pembangunan berkelanjutan, asalkan pengelolaannya dilakukan secara transparan, terukur, dan berbasis teknologi ramah lingkungan. Tantangannya bukan pada tambangnya, tetapi pada tata kelolanya.
Jika Morotai ingin menghindari kerusakan ekologis, maka kuncinya bukan menolak tambang secara total, tetapi membangun sistem pengawasan dan regulasi yang ketat. Pemerintah daerah bisa menegaskan syarat AMDAL terbuka, memastikan keterlibatan masyarakat lokal, dan mengarahkan sebagian besar manfaat ekonomi untuk pembangunan sosial: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dengan demikian, tambang tidak lagi menjadi simbol perampasan, melainkan katalis fiskal menuju kemandirian.
Selain itu, potensi tambang pasir besi di Morotai bisa menjadi sumber daya strategis untuk menopang industri pengolahan logam di wilayah Maluku Utara yang kini mulai tumbuh. Jika Morotai mampu memosisikan diri bukan hanya sebagai penghasil bahan mentah, tetapi sebagai bagian dari rantai nilai industri, maka peluang fiskal dan lapangan kerja akan meningkat tajam. Morotai tidak harus menjadi korban eksploitasi, ia bisa menjadi mitra strategis pembangunan.
Kekhawatiran terhadap lingkungan tetap valid dan harus menjadi alarm moral. Namun harus diakui pula, tanpa kekuatan fiskal, kebijakan konservasi pun sulit dijalankan. Pemerintah daerah yang miskin fiskal tidak akan mampu melindungi lingkungan secara efektif karena bergantung pada anggaran pusat yang terbatas dan sering terlambat. Fiskal yang kuat justru memberi ruang bagi Morotai untuk memperkuat sistem perlindungan ekologisnya sendiri.
Karena itu, pendekatan paling bijak bukanlah menolak tambang secara membabi buta, melainkan menempatkannya dalam kerangka pembangunan yang lebih besar — pembangunan yang berbasis kontrol sosial, teknologi bersih, dan distribusi hasil yang adil. Pemerintah daerah perlu menyiapkan desain besar: siapa yang menambang, bagaimana menambang, dan untuk kepentingan siapa tambang itu dilakukan. Transparansi menjadi kata kunci agar tambang tidak berubah menjadi kutukan baru.
Morotai memang harus berhati-hati, tetapi juga tidak boleh takut. Pulau ini punya kesempatan untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak harus saling meniadakan. Dengan tata kelola yang berani dan partisipatif, Morotai bisa menemukan keseimbangannya sendiri: menambang dengan bijak, membangun dengan sadar, dan menjaga dengan cinta. Sekian! (*)