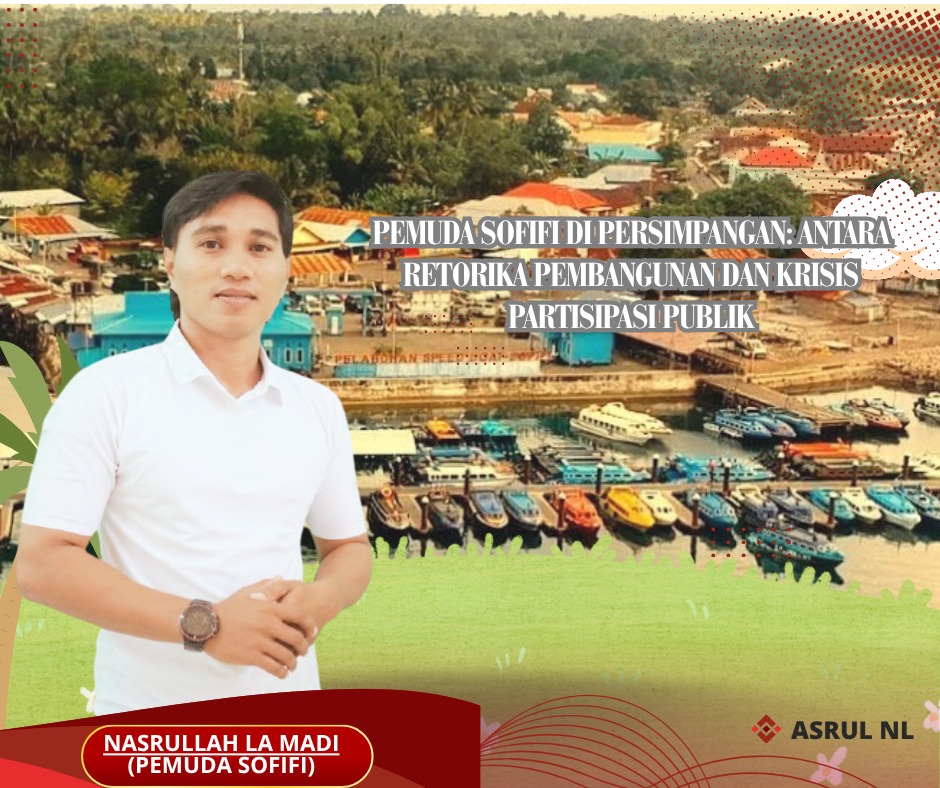Oleh: Nasrullah Lamadi
Pemuda Sofifi
_____________
SOFIFI perlahan mulai berubah. Gedung-gedung pemerintahan mulai dibangun menjulang, jalan-jalan baru dibuka, dan papan proyek pembangunan terpampang di mana-mana. Namun di balik kemegahan itu, ada yang pelan-pelan hilang: jiwa sosial pemuda Sofifi.
Kota yang digadang-gadang menjadi jantung administrasi Provinsi Maluku Utara itu kini menghadapi paradoks. Modernisasi fisik tidak beriringan dengan kemajuan sosial. Infrastruktur dibangun, tetapi kesadaran kritis pemudanya justru terpuruk. Organisasi kepemudaan lebih banyak berfungsi sebagai pelengkap seremoni ketimbang ruang konsolidasi gagasan. Di sisi lain, negara dan elite lokal tampak nyaman dengan situasi ini, seolah pasifnya pemuda adalah jaminan stabilitas politik.
Retorika Pemberdayaan
Dalam pidato-pidato resmi, pemerintah sering menyebut pemuda sebagai “penerus bangsa” atau “mitra pembangunan”. Namun istilah itu kerap berhenti di tataran simbolik. Di Sofifi, program pemberdayaan pemuda lebih banyak berbentuk kegiatan seremonial tahunan, pelatihan singkat tanpa keberlanjutan, atau pembentukan organisasi yang dikendalikan dari atas.
Alih-alih melahirkan pemuda yang kritis dan independen, praktik semacam ini justru menumbuhkan budaya kepemudaan yang bergantung pada proyek. Banyak komunitas muda tumbuh bukan karena kesadaran sosial, melainkan karena akses terhadap dana hibah. Akibatnya, ruang partisipasi publik dikomodifikasi, menjadi sekadar ruang distribusi anggaran, bukan ruang diskusi ide. Padahal, United Nations Development Programme (UNDP, 2022) menunjukkan bahwa negara dengan partisipasi aktif pemuda dalam kebijakan publik memiliki 20 persen lebih banyak kebijakan yang berpihak pada generasi muda. Artinya, ketika pemuda hanya dijadikan objek proyek, bukan subjek perubahan, maka arah pembangunan akan kehilangan legitimasi sosialnya.
Secara demografis, pemuda berusia 16–30 tahun menyumbang 25 persen populasi Indonesia (BPS, 2023). Namun representasi mereka di lembaga legislatif masih sangat rendah. Di Sofifi, hanya dua pemuda yang berhasil menembus DPRD Kota Tidore Kepulauan, capaian yang layak diapresiasi, tetapi juga patut dikritisi.
Pertanyaan mendasarnya: apakah kehadiran mereka mampu mengubah struktur politik yang sudah mapan dan elitis? Representasi tidak otomatis berarti transformasi. Ketika sistem politik lokal masih beroperasi dalam logika patronase dan kompromi, keberadaan pemuda di parlemen berisiko hanya menjadi wajah muda dari sistem lama.
Pemuda Sofifi seharusnya tidak puas dengan sekadar representasi simbolik. Mereka harus mendesak dibukanya kanal partisipasi publik yang substantif: public hearing, forum konsultasi kebijakan, musyawarah rencana pembangunan yang transparan, dan mekanisme akuntabilitas sosial. Politik partisipatif tidak lahir dari seremoni, tetapi dari keberanian menuntut ruang dialog yang sejajar dengan pemerintah.
Pemuda dengan Kesadaran Rendah
Di atas kertas, Sofifi memiliki modal intelektual yang cukup. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 19–26 tahun mencapai sekitar 43 persen, sebagian besar sudah menempuh pendidikan tinggi. Namun ironi muncul: semakin tinggi pendidikan, semakin rendah partisipasi sosial. Fenomena ini menunjukkan belum maksimalnya sistem pendidikan dalam menumbuhkan civic engagement dan public reasoning. Pendidikan kita masih berorientasi pada ijazah, bukan kesadaran sosial. Perguruan tinggi belum mampu berperan sebagai laboratorium gagasan publik, melainkan sekadar tempat transit menuju pekerjaan formal.
Akibatnya, generasi muda Sofifi tumbuh dalam ruang sosial yang miskin imajinasi politik. Mereka apatis terhadap kebijakan publik, skeptis terhadap organisasi sosial, dan menggantungkan perubahan pada figur pemimpin, bukan pada inisiatif kolektif.
Selain hal tersebut perubahan gaya hidup turut memperparah situasi ini. Media sosial membentuk pola komunikasi instan yang berorientasi pada citra. Aktivisme diukur dari seberapa sering unggahan diklik, bukan seberapa besar dampaknya di lapangan. Di Sofifi, gaya hidup konsumtif mulai menggantikan nilai gotong royong dan solidaritas komunitas. Pemuda lebih sibuk mengejar eksistensi digital daripada merumuskan masa depan sosial daerahnya.
Ironisnya, elite politik justru memanfaatkan budaya hedonis ini sebagai strategi depolitisasi. Selama pemuda sibuk di ruang maya, mereka tidak akan mengganggu kenyamanan status quo. Maka, tidak mengherankan jika banyak forum diskusi pemuda perlahan mulai hilang dan berubah menjadi ruang basa-basi administratif.
Menuju Politik Kesadaran
Kritik terhadap situasi ini bukan untuk menumbuhkan pesimisme, melainkan untuk mendorong perubahan paradigma. Pemuda Sofifi harus beranjak dari posisi “penonton pembangunan” menjadi “pengambil keputusan sosial”.
Politik kesadaran menuntut dua hal. Pertama, keberanian melawan logika proyek. Gerakan pemuda harus dibiayai oleh solidaritas dan kemandirian, bukan sekadar proposal kegiatan. Kedua, kemampuan membangun jaringan pengetahuan lintas sektor, antara komunitas, kampus, media, dan lembaga pemerintahan. Hanya dengan cara itu pemuda bisa mengembalikan fungsi sosialnya sebagai penyambung nalar publik dan penjaga moral sosial.
Pemuda Sofifi tidak kekurangan potensi; yang hilang adalah arah. Mereka butuh ruang, tetapi juga harus berani menciptakan ruang. Menuju tahun 2026 seharusnya menjadi momentum untuk membangun ekosistem partisipasi baru, berbasis pada literasi sosial, dialog kritis, dan solidaritas lintas kelas. Gerakan literasi pemuda, komunitas riset kecil, hingga kegiatan seni tradisi bisa menjadi ruang tanding melawan apatisme. Sebab perubahan sosial tidak selalu lahir dari gedung DPRD, tetapi bisa bermula dari forum kecil di sudut kampung yang berani mempertanyakan kebijakan publik.
Sofifi membutuhkan pemuda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berani bersuara. Sebab sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang diam, melainkan oleh mereka yang melawan keheningan. (*)