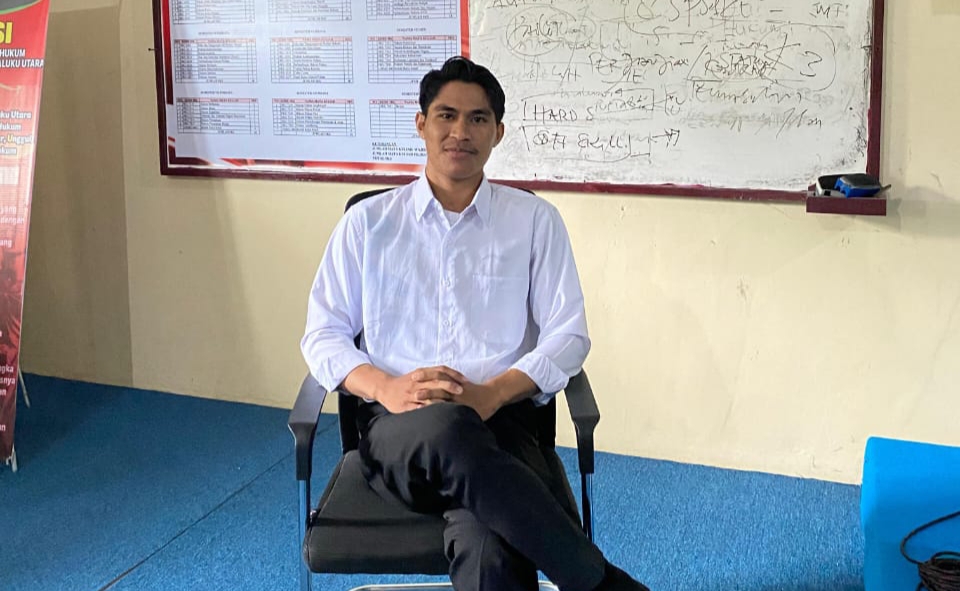Oleh: Ardi Turege
Wakil Presiden BEM FH UMMU, Ketua UKM LDRS FH UMMU, Pegiat Law Fhighters Comunity
________________
CIRI utama dalam negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (constitucional democracy) adalah adanya satu lembaga yang independen dan tidak memihak (independent and impartial). Dalam hal ini maka kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang di maksud.
Dalam sistem negara modern, kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan dan pilar yang penting. Kekuasaan kehakiman (Judiciary) merupakan cabang yang di organisir secara tersendiri dari organisasi lain. John Alder, menyatakan ” The principle of separation of powers is particularly important for the Judiciary“.
Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum memegang peran yang sangat penting sebagai benteng terakhir demokrasi dan keadilan. Ia bukan sekadar alat pelengkap sistem ketatanegaraan, tetapi pilar utama dalam menjaga hak asasi, menegakkan hukum, dan menjamin keadilan substantif bagi rakyat. Namun, marwah kekuasaan ini perlahan memudar, bukan karena tekanan eksternal semata, melainkan justru oleh tangan-tangan hakim itu sendiri.
Di Indonesia, berdasarkan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal ini menegaskan sifat independen dari badan peradilan itu sendiri.
Menurut Montesqiaw dalam teori Trias Politica, kekuasaan negara terbagi menjadi tiga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif dan kekuasaan yudikatif menjadi tonggak terkahir untuk menegakan dan mengadili. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, fungsi-fungsi dari ketiga lembaga tersebut terpisah antara satu dengan yang lain untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang checks and balances.
Pemisahan kekuasaan kehakiman ini untuk menciptakan independensi peradilan. Karena prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) untuk menghendaki para hakim bekerja dengan independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. (Jimly Asshiddiqie. 2015.310).
Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan menjadi pra syarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi hakim harus melekat pada pribadi hakim, dan hal ini harus terwujud dan tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, atas setiap perkara yang diperiksa dan diadilinya. Independensi hakim juga terikat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Karena independensi pengadilan akan terwujud dalam kemandirian hakim.
Kekuasaan kehakiman (judicial power) harus berdiri independen agar mampu menegakkan hukum secara objektif dan imparsial. Dalam konteks ini, hakim adalah perwujudan kekuasaan yudikatif yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.
Namun, praktik di lapangan sering menunjukkan deviasi. Alih-alih menjadi tonggak hukum dan keadilan, hakim justru terjerumus dalam hawa nafsunya. Tidak sedikit hakim yang tergoda oleh kekuasaan, kekayaan, dan kedekatan politik. Mereka lupa bahwa palu hakim bukan alat kompromi, melainkan simbol integritas dan kebenaran yang harus ditegakkan.
Hans Kelsen dalam teori Stufenbau Teori (hierarki norma), menempatkan putusan hakim sebagai bagian dari norma konkret yang menurunkan norma hukum umum ke dalam tindakan spesifik. Oleh karena itu, jika hakim menyalahgunakan kewenangannya, maka norma hukum menjadi kehilangan kekuatan dan kepastian hukumnya melemah.
Hal ini berimplikasi terhadap publik yang semakin skeptis terhadap institusi peradilan, ketika vonis-vonis ganjil kerap muncul, kasus-kasus besar ditangani dengan lunak, sementara masyarakat kecil dihukum berat karena pelanggaran ringan. Ketika keadilan dipertontonkan sebagai transaksi, bukan sebagai prinsip of law and supremasi of law, maka saat itulah marwah kekuasaan kehakiman runtuh di hadapan publik, oleh ulah parah pengawalnya sendiri.
Kekuasaan kehakiman yang diselewengkan oleh hakim, menyebabkan ketidakadilan yang sistemik. Hakim seharusnya menjadi “lidah undang-undang”, dan tonggak keadilan. Namun, hakim mempertontonkan banyak putusan yang kontroversial dan justru menjadi penafsir liar yang berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Seperti putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, menjadi kontroversial di kalangan masyarakat dan akademisi. Dan masih banyak lagi putusan hakim yang kontroversial. Akibatnya, putusan hakim kehilangan legitimasi sosial dan berimplikasi kepercayaan publik terhadap peradilan runtuh tak terkendali.
Belum lagi dengan beberapa hakim yang melakukan perbuatan-perbuatan Korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kurun waktu 2010-2025, ada 31 hakim yang terjerat kasus korupsi yang ditangani komisi anti korupsi tersebut. Dan hal ini menjadikan hakim sebagai aparat penegak hukum menempati posisi pertama, sebagai aparat hukum yang melakukan korupsi. Di ikuti dengan peringkat kedua penegak hukum yang terjerat kasus korupsi adalah pengacara dengan jumlah 19 orang, kemudian jaksa sebanyak 13 orang, dan polisi 6 orang.
Berbagai kasus korupsi di atas, yang melibatkan hakim, seperti suap, gratifikasi, hingga pengaturan vonis, menjadi bukti bahwa marwah kehakiman telah tercemar. Hal ini menunjukkan terjadinya pelanggaran serius terhadap teori etika profesi yang menekankan moralitas, integritas, dan keadilan sebagai nilai utama profesi hukum:
“”Judicial corruption atau korupsi di pengadilan terjadi dengan berjejaring, tidak hanya melibatkan satu kelompok penegak hukum, tetapi lintas institusi””.
Hilangnya marwah kekuasaan kehakiman menimbulkan krisis kepercayaan publik. Dalam teori Legitimasi Weberian, suatu lembaga hanya berfungsi efektif bila memiliki legitimasi rasional-legal. Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada sistem peradilan, maka keputusan hukum tidak akan dihormati, bahkan cenderung diabaikan.
Hakim bukan dewa, dan tidak seharusnya merasa diri sebagai penguasa keadilan yang tak tersentuh kritik. Keputusan mereka membawa dampak besar pada kehidupan orang lain, bahkan bisa mengubah arah sejarah bangsa. Namun ketika integritas tidak lagi menjadi pedoman, kekuasaan kehakiman berubah menjadi alat penindas baru. Banyak hakim melupakan sumpahnya: menegakkan hukum dengan jujur, adil, dan tidak memihak.
Beberapa kasus penangkapan hakim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di atas, menjadi bukti bahwa integritas hakim telah digadaikan demi kepentingan pribadi. Bukankah ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman yang seharusnya menjadi solusi, justru ikut menjadi bagian dari masalah di bangsa ini?
Pemulihan marwah kekuasaan kehakiman tidak cukup hanya dengan reformasi struktural, tetapi harus dimulai dari kesadaran personal para hakim itu sendiri. Dibutuhkan keteladanan, bukan hanya dari pimpinan lembaga peradilan, tetapi juga dari hakim-hakim di semua tingkat.
Transparansi proses peradilan, pengawasan etik yang efektif, dan pendidikan berkelanjutan tentang etika profesi harus terus diperkuat. Masyarakat pun perlu diberi ruang untuk mengawasi, mengkritik, dan mengevaluasi sistem peradilan tanpa rasa takut.
Ketika hakim tidak lagi menjadi pelita dalam gelapnya pencarian keadilan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. Dan bila kepercayaan itu runtuh, negara hukum hanya akan menjadi slogan kosong. Marwah kekuasaan kehakiman harus dijaga—bukan oleh retorika, tetapi oleh keteguhan moral para hakim itu sendiri. Jika tidak, maka kekuasaan kehakiman akan terus terpuruk—hilang di bawah tangan para penjaganya sendiri. (*)