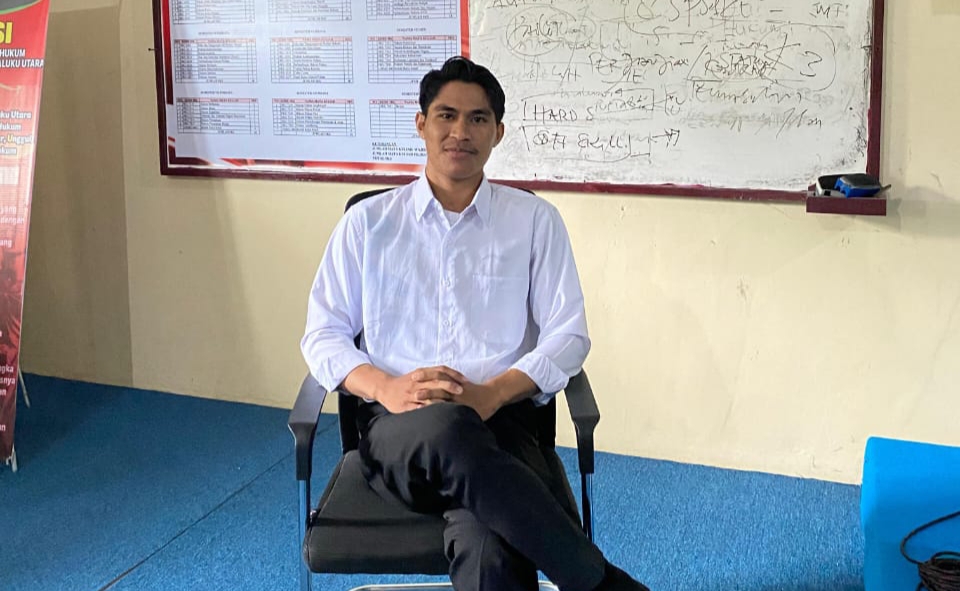Oleh: Ardi Turege
Wakil Presiden BEM FH UMMU
(Law floats in asea of ethis: hukum mengapung di atas samudra etika).
Dalam sistem pemerintahan yang ideal, pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam hal moralitas, integritas, dan etika. Mereka dipercaya oleh rakyat untuk mengelola kekuasaan demi kepentingan umum. Namun, realita yang terjadi justru sebaliknya fenomena degradasi moral di kalangan pejabat publik semakin nyata dan mengkhawatirkan.
Pejabat publik merupakan aktor sentral dalam pengelolaan negara dan pelayan masyarakat. Idealnya, mereka menjunjung tinggi etika, moralitas, dan integritas dalam setiap tindakan. Namun, dalam kenyataan yang kita hadapi hari ini, tidak sedikit pejabat publik yang justru terjerumus dalam berbagai praktik amoral seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, hingga gaya hidup mewah yang tak sesuai dengan logika penghasilan resmi, hingga ketidakpedulian terhadap nasib rakyat. Fenomena ini dikenal sebagai degradasi moral, sebuah gejala penurunan nilai-nilai luhur yang semestinya menjadi fondasi dalam kepemimpinan publik, semua ini mencerminkan hilangnya kompas moral dalam menjalankan amanah.
Menurut Brown, Treviño, dan Harrison (2005), etika kepemimpinan adalah demonstrasi perilaku normatif yang sesuai dengan nilai moral melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal, serta promosi perilaku yang sesuai melalui komunikasi, penguatan, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pemimpin yang etis bukan hanya bertindak benar, tetapi juga mendorong lingkungan yang mendukung perilaku etis.
Kohlberg (1971) menjelaskan bahwa perkembangan moral seseorang berlangsung dalam tiga tingkat: pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Banyak pejabat publik yang berhenti pada tahap konvensional, di mana tindakan dilakukan hanya untuk menaati hukum atau menjaga citra, bukan karena kesadaran moral sejati. Tanpa kematangan moral yang sejati, kekuasaan mudah disalahgunakan.
Kejadian demi kejadian yang mencoreng nama baik institusi pemerintahan terus muncul. Mulai dari kasus suap dan gratifikasi, penggelapan dana publik, hingga keterlibatan dalam sindikat kejahatan terorganisir. Yang lebih memprihatinkan, kasus-kasus tersebut tidak hanya dilakukan oleh pejabat level bawah, melainkan juga oleh mereka yang menduduki posisi strategis. Dalam banyak kasus, pelaku bahkan tampak tidak menunjukkan rasa bersalah sebuah indikator bahwa nilai-nilai moral telah terdegradasi serius. Tak terkecuali dengan Anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) sebagai Perwakilan Rakyat.
Tahun 2025 seharusnya menjadi momentum perubahan arah politik Indonesia Emas menuju pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Namun, harapan itu kembali terkubur di balik rentetan kasus yang menimpa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga yang semestinya menjadi wakil suara rakyat. Alih-alih menjadi garda terdepan penjaga demokrasi, DPR kini semakin tenggelam dalam lumpur degradasi moral yang kian mengkhawatirkan.
Salah satu gejala paling nyata dari degradasi moral DPR 2025 adalah praktik politik transaksional yang terus mengakar. Proses legislasi bukan lagi soal kepentingan rakyat, tetapi soal “siapa bayar, dia dapat.” Banyak rancangan undang-undang yang dinilai sarat kepentingan elit (UU TNI No 3 Tahun 2025, UU BUMN No 1 Tahun 2025, UU Minerba No 2 Tahun 2025), yang disusun secara kilat tanpa partisipasi publik yang memadai. Rakyat hanya dijadikan penonton, sementara kepentingan oligarki semakin kuat mengendalikan parlemen.
Degradasi moral tak hanya tampak dari korupsi, tetapi juga dari perilaku sehari-hari para wakil rakyat. Banyak yang tak hadir dalam sidang, tertidur saat pembahasan penting, atau malah sibuk dengan kepentingan pribadi di tengah krisis nasional.
Memasuki 11 tahun pemerintahan Indonesia oleh sang nakhoda baru, harapan kita adalah menuju negara yang sebagaimana dimaksud dalam Batang Tubuh Konstitusi kita (UUD NRI 1945). Bukannya mencapai kesejahteraan dan kemakmuran DPR, justru berpesta di Senayan. Bukan pesta rakyat, melainkan pesta tunjangan yang dinaikan. Gedung megah itu kembali bergema bukan (not) karena debat panas soal nasib buruh atau petani, tapi karena kegembiraan menyambut naiknya tunjangan bagi para wakil rakyat.
Di ruang rapat yang ber-AC dingin dan kursi empuk, keputusan diambil dengan mulus. Tunjangan naik, demi “meningkatkan kinerja”. Tapi di luar sana, rakyat antre sembako, anak-anak putus sekolah, dan harga bahan pokok terus merangkak naik tanpa ampun.
Ironi itu begitu nyata:
Di saat rakyat menggigil menunggu untuk kemakmuran yang berkelanjutan malah hal itu tak kunjung datang. Para wakilnya justru menari dalam gemerlap angka rupiah tambahan. Mereka berjoget di atas tumpukan janji yang tak ditepati.Sementara rakyat menangis dalam sunyi, hanya ditemani harapan yang kian pudar.
DPR semestinya menjadi contoh moral dan etika berpolitik yang luhur. Namun realitas berbicara lain. Generasi muda kehilangan panutan karena yang mereka lihat adalah pertunjukan arogansi kekuasaan, bukan integritas. DPR kehilangan kepercayaan publik karena lebih sibuk membela kepentingan sendiri daripada memperjuangkan nasib rakyat.
Haruskah Kita Menormalisasi Kemerosotan Ini?
Jawabannya: Tidak. Rakyat tidak boleh diam. Demokrasi tidak bisa berjalan sehat jika wakil-wakil rakyatnya justru menjadi sumber penyakit. Sudah saatnya publik lebih kritis, media lebih berani, dan lembaga penegak hukum lebih tegas. Reformasi bukan sekadar jargon, tetapi harus diwujudkan dalam pembenahan total sistem politik kita terutama di tubuh DPR.
Salah satu faktor utama penyebab degradasi moral adalah lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Ketika sistem hukum tidak berjalan tegas, dan budaya hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah tetap dipertahankan, maka ruang bagi penyimpangan moral semakin terbuka lebar. Selain itu, dorongan gaya hidup konsumtif dan kompetisi politik yang kotor kerap menjadikan jabatan sebagai alat mencari kekayaan pribadi, bukan sarana pengabdian.
Krisis moral ini juga menciptakan efek domino. Ketika pejabat publik menunjukkan perilaku menyimpang, hal itu menular ke lapisan birokrasi di bawahnya, bahkan sampai ke masyarakat. Rakyat menjadi apatis, kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan, dan berujung pada melemahnya partisipasi publik dalam demokrasi.
Untuk memulihkan moralitas pejabat publik, diperlukan reformasi menyeluruh, tidak hanya dalam aspek hukum dan kelembagaan, tapi juga dalam aspek budaya dan pendidikan moral. Penguatan sistem transparansi, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan menjadi kunci penting. Di samping itu, regenerasi kepemimpinan yang menjunjung etika harus didorong bukan hanya cerdas, tapi juga berintegritas.
Pejabat publik harus kembali menyadari bahwa jabatan adalah amanah, bukan privilese. Selama moralitas dikorbankan demi kepentingan pribadi dan kelompok, maka cita-cita keadilan sosial akan terus menjadi ilusi. Sudah waktunya kita tidak hanya menuntut perubahan dari atas, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa moralitas adalah fondasi utama dalam membangun bangsa. (*)