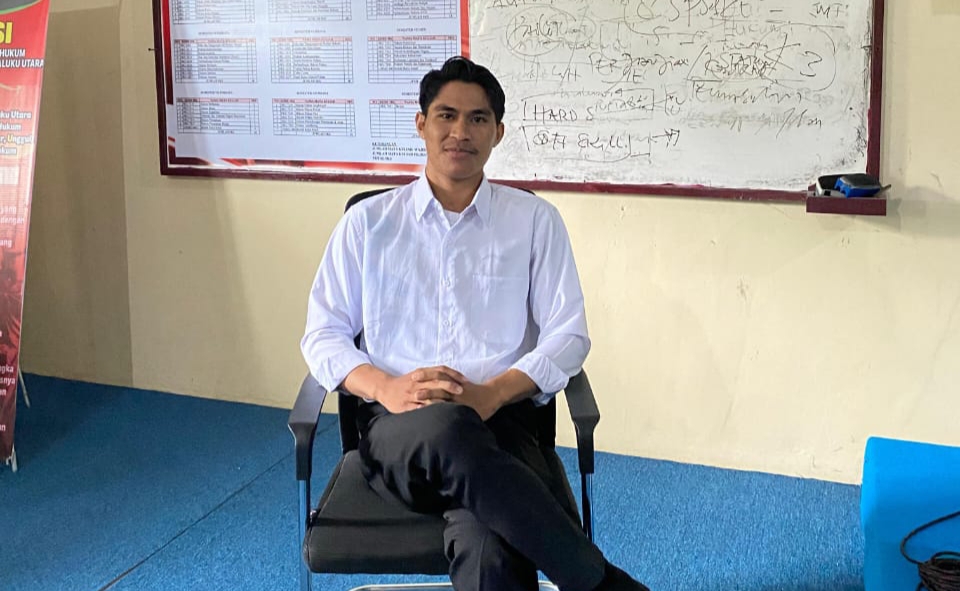Oleh: Ardi Turege
Wakil Ketua BEM FH UMMU
_____________________
DEMOKRASI dibangun di atas empat pilar utama: kebebasan berpendapat, supremasi hukum, pemilu yang adil, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun, apa jadinya ketika satu demi satu pilar-pilar demokrasi itu dipatahkan dan dihancurkan tak berkeping-keping, bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh tangan kekuasaan sendiri. Bahkan lebih tragis, ketika pelakunya adalah aparat yang seharusnya menjaga bukan merusak.
Aparat kepolisian, dalam banyak peristiwa, telah menunjukkan wajah yang jauh dari cita-cita demokrasi. Mereka bukan lagi simbol perlindungan rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam konstitusi, melainkan menjadi aktor utama dalam represi dan pembungkaman. Ketika rakyat bicara, mereka dibungkam. Ketika rakyat berdiri, mereka dijatuhkan. Ketika rakyat melawan, mereka dipukul, ditangkap, dicap sebagai pengacau pembuat onar dan lain sebagainya.
Di jalan-jalan kota, suara demonstrasi dibalas dengan gas air mata. Di pelosok negeri, laporan pelanggaran dibalas dengan intimidasi. Di ruang digital, kritik dibalas dengan pelacakan dan ancaman. Semua ini menciptakan satu kesimpulan pahit: pilar demokrasi tidak tumbang dengan sendirinya. Ia dihancurkan secara sistematis, diinjak-injak oleh kaki busuk aparat kepolisian yang kehilangan rasa malu dan rasa tanggung jawab.
Lebih menyakitkan lagi, praktik kekerasan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) ini sering kali berlindung di balik dalih “keamanan negara”. Seolah-olah suara rakyat adalah ancaman, bukan harapan. Seolah-olah kritik adalah dosa, bukan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Ketika hukum berpihak pada seragam, bukan pada kebenaran, maka yang tersisa hanyalah tirani yang tersamar.
Dan kita melihat akibatnya: rasa takut menggantikan keberanian, apatis menggantikan harapan, dan diam menggantikan suara. Demokrasi tidak mati dalam satu malam, tapi perlahan hancur, dicabik oleh mereka yang seharusnya menjaga.
Selama aparat kepolisian tidak berani bercermin dan membersihkan dirinya dari budaya kekerasan, demokrasi akan terus patah. Tidak ada yang bisa dibangun di atas fondasi yang retak. Keadilan tidak bisa tumbuh di bawah bayang-bayang teror. Dan kebebasan tidak mungkin hidup ketika yang memegang tongkat, memegang kuasa penuh atas hidup dan mati suara rakyat.
Demokrasi, dalam cita-cita idealnya, adalah sistem yang lahir dari rahim partisipasi rakyat, tumbuh di atas fondasi kebebasan, dan berdiri tegak oleh penegakan hukum yang adil. Namun di negeri ini, wajah demokrasi tampak tak lagi utuh. Ia retak. Luka. Hancur berkeping-keping dan kepingan itu kini tergilas oleh kaki busuk aparatur negara yang mestinya menjadi pelindung rakyat: kepolisian.
Berulang kali kita menyaksikan bagaimana suara rakyat dibungkam secara paksa. Demonstrasi damai dihadang, dibubarkan, bahkan dibasahi gas air mata dan darah. Para mahasiswa dipukuli, aktivis dikriminalisasi, wartawan diintimidasi, dan warga biasa dipaksa diam. Ruang publik dipersempit. Kritik terhadap kekuasaan diputarbalikkan menjadi ancaman terhadap negara. Kepolisian yang seharusnya menjadi pengayom justru berubah menjadi algojo.
Lantas, untuk siapa aparat kepolisian bekerja? Untuk rakyat yang membayar gaji mereka melalui pajak? Atau untuk kekuasaan yang tak mau diganggu kenyamanannya? Ketika aparat lebih sibuk melayani kepentingan elite-elite negara daripada melindungi rakyat, maka demokrasi berubah menjadi sandiwara murahan panggung kekuasaan yang hanya berpihak pada mereka yang duduk di singgasana.
Tidak ada demokrasi jika rakyat tak merasa aman untuk bersuara. Tidak ada demokrasi jika hukum hanya tajam ke bawah. Tidak ada demokrasi jika polisi menjadi alat represi, bukan representasi keadilan.
Wajah demokrasi di negeri ini makin hari makin buruk rupa. Ia tak lagi bersinar sebagai simbol harapan rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi, tetapi menjelma menjadi wajah yang lebam dan penuh luka. Dan luka-luka itu bukan hanya simbolis. Ia nyata menyisakan trauma, ketakutan, dan kehilangan kepercayaan pada sistem yang ada di negara ini.
Yang lebih mengerikan adalah pembiaran sistemik. Ketika kekerasan aparat dianggap wajar. Ketika pelanggaran hak asasi dibungkam dengan narasi “demi stabilitas”. Ketika pelaku kekerasan berpangkat naik, sementara korban kehilangan suara. Di titik inilah demokrasi benar-benar hancur karena ia tidak sekadar diserang, tapi dikhianati dari dalam.
Sudah saatnya kita berhenti menormalisasi kekerasan yang dibalut seragam. Demokrasi tidak bisa hidup dalam atmosfer ketakutan. Demokrasi tidak akan tumbuh jika aparat terus menjadi alat pembungkam. Dan demokrasi pasti mati jika rakyat berhenti percaya bahwa suara mereka berarti. Selama kaki busuk kepolisian masih menari di atas penderitaan rakyat, maka jangan heran jika demokrasi terus-menerus patah berkeping-keping.
Di atas kertas, Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Tapi di jalan-jalan, di ruang-ruang publik, dan di layar ponsel rakyat, demokrasi itu sudah remuk, retakannya menganga, serpihannya berserakan di bawah sepatu-sepatu lars yang menginjak tanpa ragu. Ia bukan lagi sistem pemerintahan, ia menjadi ilusi, topeng yang sudah usang, dipakai untuk menutupi wajah otoritarianisme yang perlahan kembali tumbuh di balik seragam dan senjata.
Kepolisian yang seharusnya menjadi pengayom, telah menjelma menjadi mesin kekuasaan. Kekerasan tak lagi menjadi pelanggaran, melainkan protokol. Kritik dianggap ancaman, suara rakyat diperlakukan sebagai gangguan. Di balik tameng hukum, aparat menjelma hakim jalanan menentukan siapa yang berhak bicara dan siapa yang harus dibungkam.
Apa yang terjadi pada demokrasi ketika rakyat takut bersuara? Ketika mahasiswa dibungkam, aktivis diculik, jurnalis diintimidasi, dan pelanggaran HAM dijawab dengan senyum sinis serta rilis pers kosong? Demokrasi itu tidak tumbang seketika, ia dikikis perlahan oleh kaki-kaki busuk yang melangkah di atas hukum tanpa pernah menyentuh keadilan.
Setiap gas air mata yang ditembakkan ke wajah demonstran adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Setiap pentungan yang diayunkan ke tubuh rakyat adalah deklarasi bahwa hukum kini tak berpihak. Demokrasi menjadi sandera, dan para penculiknya memakai lencana.
Kita hidup dalam paradoks: kebebasan dijanjikan, tapi penjara disiapkan. Rakyat disuruh percaya pada hukum, tapi hukum hanya bekerja untuk yang berkuasa. Polisi bukan lagi penjaga ketertiban, melainkan pengabdi ketakutan. Mereka tidak berdiri di samping rakyat, tapi menginjak mimpi-mimpi mereka dengan sepatu kekuasaan yang kotor.
Jika demokrasi adalah wajah, maka kini wajah itu pecah retakannya mencerminkan luka kolektif kita sebagai anak bangsa. Dan pecahan itu dibawa pergi oleh institusi yang seharusnya menjaga, tapi justru mengkhianati. Wajah demokrasi itu kini tak bisa lagi dikenali.
Demokrasi Indonesia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Ia tidak mati tapi sekarat. Retaknya tak terlihat oleh mereka yang memuja stabilitas semu, tapi bagi rakyat yang bersuara, yang turun ke jalan, yang menuntut keadilan retakan itu terasa di setiap gas air mata yang ditembakkan, di setiap pemukulan, di setiap hilangnya nyawa tanpa pertanggungjawaban. Wajah demokrasi kita patah berkeping-keping, dan pecahannya diseret paksa oleh kaki-kaki busuk yang bersembunyi di balik seragam dan kewenangan.
Konstitusi memberi wewenang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam praktiknya, sebagian anggota kepolisian justru menjadi alat penindas rakyat. Bukannya menjunjung hukum, justru mereka menjungkirbalikannya. Bukannya menegakkan keadilan, mereka menjualnya pada kekuasaan.
Bukan rahasia lagi demonstrasi damai sering kali dibalas dengan kekerasan brutal. Aktivis dikriminalisasi. Wartawan diintimidasi. Rakyat diseret ke penjara hanya karena bersuara. Demokrasi tidak tumbang dalam satu malam. Ia dibunuh pelan-pelan, disayat oleh tindakan sewenang-wenang yang dibungkus prosedur.
Fakta menunjukan patahnya pilar-pilar Demokrasi Indonesia di bawah kaki busuk aparat kepolisian menjadi pengkhianatan terhadap konstitusi kita.
Demokrasi sejatinya berdiri di atas fondasi yang kokoh tapi nyatanya hal itu hanya menjadi angan-angan rakyat biasa. Katanya: Kedaulatan Rakyat: Tapi suara rakyat dibungkam oleh gas air mata dan pentungan. Katanya keadilan sosial: Tapi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Katanya hak asasi manusia: Tapi aparat dibiarkan melanggar tanpa konsekuensi. Katanya Rule of law: Tapi hukum tunduk pada kekuasaan, bukan kebenaran. Apa artinya demokrasi jika rakyat takut kepada aparat yang dibiayai oleh uang pajaknya sendiri? Busuknya sistem, bukan hanya sekadar oknum menjadi pengkhianatan terhadap rakyat. Sering kali, kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan aparat dibingkai sebagai kesalahan “oknum”. Tapi jika kekerasan terus berulang, jika impunitas terus dijaga, jika sistem menutupi kejahatan atas nama stabilitas, maka yang busuk bukan lagi oknumnya, yang busuk adalah sistemnya. Ini bukan lagi soal insiden. Ini adalah soal budaya institusional yang anti demokratis, yang menjadikan hukum sebagai alat represi, bukan perlindungan. Saat demokrasi menjadi korban maka berimplikasi pada: kepolisian menjadi alat politik, bukan alat hukum, maka yang menjadi korban bukan hanya mereka yang diseret, dipukul, atau ditahan. Korban utamanya adalah demokrasi itu sendiri yang seharusnya menjadi tempat rakyat bebas bicara, berpendapat, dan menuntut keadilan. Namun sangat disayangkan, kini demokrasi itu patah. Bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh tangan-tangan dalam negeri, oleh kaki-kaki busuk yang menginjak konstitusi dengan sepatu lars. Demokrasi tidak akan mati jika rakyat tetap bersuara. Tapi suara itu harus dijaga, bukan dibungkam. Karena ketika aparat menjadi musuh rakyat, maka negara telah kehilangan jiwanya.
Pada dasarnya prinsip negara yang baik adalah negara yang memegang prinsip Salus populi suprema lex esto; keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. (*)