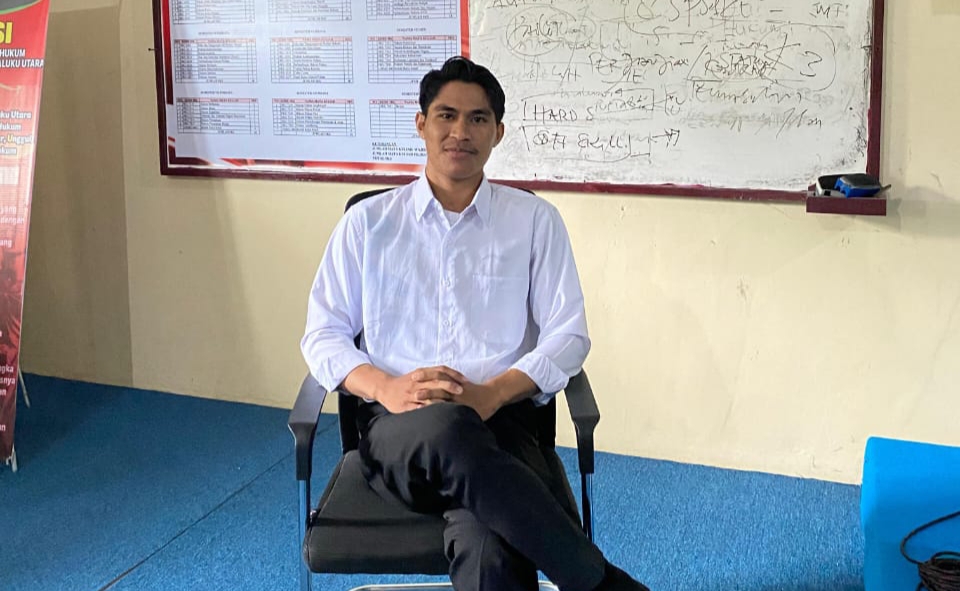Oleh: Ardi Turege
Wakil Presiden BEM FH UMMU, Ketua UKM LDRS FH UMMU, Pegiat Law Fhighters Comunity
____________
(Indonesia berdiri karena Pancasila, dan Pancasila hidup karena Indonesia. Pancasila bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dijalankan. Bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk diwujudkan dalam tindakan)
Indonesia adalah negara yang berdiri di atas keberagaman suku, ras, bahasa, agama, budaya, dan adat istiadat. Di tengah kebhinekaan yang begitu kompleks, bangsa ini memerlukan dasar yang kuat sebagai pemersatu dan penuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah Pancasila hadir sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan falsafah hidup bangsa Indonesia.
Pancasila bukan hanya hasil pemikiran rasional para pendiri bangsa, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai luhur yang tumbuh dari bumi Nusantara. Hubungan antara Indonesia dan Pancasila bersifat mendasar dan tidak terpisahkan. Keduanya saling menguatkan: Indonesia berdiri karena Pancasila, dan Pancasila hidup karena Indonesia.
Pancasila bukan hanya dasar hukum formal, tetapi juga menjadi identitas nasional. Ia merupakan cerminan dari kepribadian dan karakter bangsa Indonesia yang cinta damai, menghargai perbedaan, religius, menjunjung keadilan, dan demokratis. Dalam konteks ini, Indonesia dan Pancasila adalah satu kesatuan. Tidak ada Indonesia tanpa Pancasila, dan Pancasila hanya dapat hidup dalam konteks kebudayaan dan kebangsaan Indonesia.
Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, Pancasila adalah “identitas konstitusional” bangsa, yang mengikat seluruh sistem hukum dan tatanan sosial Indonesia. Pancasila adalah “roh” yang menghidupkan negara, bukan sekadar tulisan dalam konstitusi.
Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara, seharusnya menjadi dasar dalam setiap aspek penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Ia bukan sekadar kumpulan kata atau simbol nasionalisme belaka, tetapi fondasi filosofis, ideologis, dan konstitusional yang seharusnya hidup dalam tindakan nyata dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila secara yuridis dan filosofis menempati posisi tertinggi dalam sistem norma hukum Indonesia. Dalam kerangka teori hukum Hans Nawiasky, Pancasila dapat dipahami sebagai (staatsfundamentalnorm) norma fundamental negara yang menjadi sumber dan dasar pembentukan seluruh sistem hukum yang berlaku. Namun, dalam praktik ketatanegaraan dan kehidupan sosial-politik, Pancasila kerap kehilangan substansi dan hanya menjadi simbol kosong kiasan tanpa makna.
Hans Kelsen, dalam teori Stufenbau Teori (teori jenjang norma), menyatakan bahwa sistem hukum tersusun secara hierarkis, di mana norma-norma yang lebih rendah bersumber dari norma yang lebih tinggi. Pada puncaknya, terdapat Grundnorm (norma dasar) atau staatsfundamentalnorm yang menjadi legitimasi dari seluruh sistem hukum.
Dalam konteks Indonesia, Pancasila diposisikan sebagai staatsfundamentalnorm, di atas Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan. Pasal 2 UU No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (UU PPP) menyatakan ” Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”.
Prof. Jimly Asshiddiqie, yang menyebut Pancasila sebagai identitas konstitusional bangsa dan puncak norma dalam hierarki norma hukum di Indonesia. Beliau juga, menekankan bahwa Pancasila bukan hanya idealisme, tetapi dasar filosofis dan konstitusional yang bersifat mengikat dalam sistem hukum dan kehidupan kenegaraan.
Implikasi teoritisnya: seluruh produk hukum dan kebijakan negara seharusnya berakar dan konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Ketika nilai-nilai ini diabaikan, maka sistem hukum kehilangan legitimasi moral dan filosofisnya.
Pancasila sebagai norma fundamental memiliki implikasi luas dalam sistem hukum, tata pemerintahan, kehidupan sosial, dan karakter bangsa. Tidak cukup hanya menghormati Pancasila secara simbolik atau tekstual semata, kita harus menerjemahkan nilai-nilainya ke dalam hukum, kebijakan, dan tindakan nyata dalam bangsa ini.
Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie: “Pancasila tidak cukup hanya dihafal, tetapi harus dipahami, dijalankan, dan dijadikan landasan dalam kehidupan hukum dan kenegaraan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai norma dasar yang hidup dan bekerja, maka kita menjaga identitas dan integritas bangsa Indonesia secara utuh. Pancasila bukan hanya untuk dibaca dalam upacara atau tertulis di dinding kantor pemerintahan. Pancasila harus dihidupi dan diamalkan dalam kehidupan nyata, baik oleh rakyat maupun oleh penyelenggara negara.
Namun realitas hari ini menunjukkan ironi yang amat mendalam:
Pancasila semakin sering dipuja dalam wacana-wacana pejabat tetapi dilupakan dalam perbuatan. Ia dibingkai dalam pidato kenegaraan, dicetak di buku pelajaran, dan dikutip dalam berbagai dokumen resmi, namun jarang benar-benar mewarnai kebijakan publik, penegakan hukum, atau perilaku para pemimpin bangsa. Dengan kata lain, Pancasila telah direduksi menjadi sekadar kiasan tanpa makna.
Kita dapat melihat Pancasila dalam Praksis: Antara Idealisme dan Realitas!!
Di atas kertas, Pancasila menjanjikan tatanan masyarakat yang adil, humanis, demokratis, dan bersatu. Namun dalam kenyataannya: Sila Keadilan Sosial tak terlihat di tengah ketimpangan ekonomi dan akses yang timpang terhadap layanan publik. Rakyat masih bertaruh dengan kemiskinan yang tidak ada akhir, sementara pejabat berjoget dengen tunjangan yang di naikan.
Sila Kemanusiaan dilanggar oleh pelanggaran HAM, kekerasan negara, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Gerakan Demonstrasi yang katanya tonggak dari sayap demokrasi di paksa bubar dengen dalih ketertiban oleh aparat keamanan negara.
Sila Kemanusiaan yang beradab kehilangan marwa, pejabat bukannya mendengar tangisan suara rakyat yang bergemuruh di seluruh penjuru negeri, dan pelosok-pelosok desa, justru ditanggapi dengan suara candaan dan hinaan, ini menandakan moral pejabat publik sedang tidak baik-baik saja.
Sila Persatuan justru retak akibat politisasi identitas dan narasi intoleransi yang dibiarkan berkembang. Sila Kerakyatan dilecehkan oleh oligarki politik dan demokrasi prosedural yang jauh dari substansi kedaulatan rakyat. Sila Ketuhanan sering dijadikan alat justifikasi moral untuk kepentingan politik praktis, bukan nilai spiritual universal.
Dalam kondisi ini, Pancasila tidak lagi menjadi staatsfundamentalnorm dalam arti yang sesungguhnya, tetapi berubah menjadi retorika politis, alat legitimasi kekuasaan, dan hiasan konstitusional belaka atau menjadi Simbol Ideologis yang terpinggirkan.
Mengutip filsuf Jürgen Habermas, suatu negara akan kehilangan legitimasi jika ideologi resminya tidak lagi terinternalisasi dalam tindakan nyata aktor negara. Dalam konteks ini, ketika elit politik hanya menjadikan Pancasila sebagai jargon dan formalitas tanpa implementasi substansial, maka Pancasila terperangkap dalam simbolisme. Ia kehilangan nilai sebagai dasar tindakan moral dan hukum, menjadi “simbol ideologis yang terpinggirkan”.
Apakah sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakat yang masih terbelah antara kaya dan miskin secara ekstrem? Apakah “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” tercermin dalam aparat yang represif atau hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Di mana “Persatuan Indonesia” ketika politik identitas dan polarisasi justru dibiarkan tumbuh subur demi kepentingan kekuasaan?
Lebih jauh lagi, Pancasila telah dijadikan alat legitimasi oleh banyak pihak—baik oleh penguasa untuk mempertahankan status quo, maupun oleh elit politik untuk membungkus kepentingan pragmatis dengan jargon kebangsaan. Dalam suasana seperti ini, Pancasila bukan lagi norma dasar yang membimbing arah negara, melainkan hanya ornamen yang dipakai saat diperlukan, lalu disimpan kembali ketika menghalangi kepentingan.
Solusinya:
Jika negara ingin mengembalikan legitimasi moral dan filosofisnya, maka Pancasila harus dihidupkan kembali dalam praksis kenegaraan: Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan utama dalam perumusan kebijakan publik. Mewujudkan sistem hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan berpihak pada keadilan sosial.
Memperkuat pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai hidup, bukan sekadar hafalan.
Maka, perlu keberanian kolektif untuk membawa kembali Pancasila dari dunia simbolik menuju realitas praksis. Ia harus dihidupkan kembali dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat, dalam hukum yang benar-benar adil, dalam birokrasi yang melayani, dan dalam kehidupan sosial yang saling menghormati perbedaan.
Jika tidak, maka selama itu pula Pancasila akan tetap menjadi staatsfundamentalnorm yang mati suri, hadir di teks, hilang dalam konteks—sekadar kiasan tanpa makna di negeri yang katanya berdasarkan filosofinya. (*)