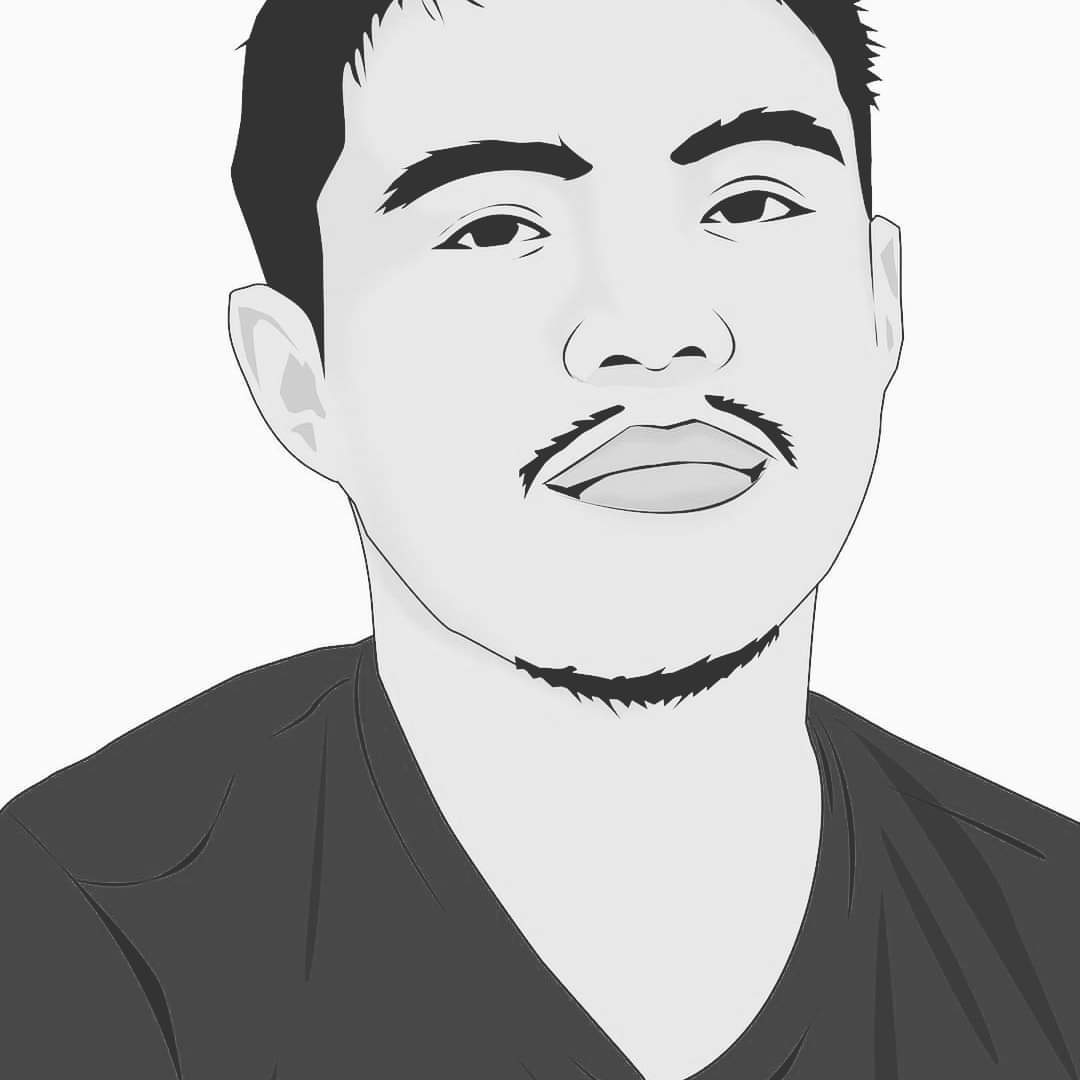Oleh: Ali Akbar Djaguna
______________
ADA rasa hening yang berbeda setiap kali kalender menandai tanggal 10 November. Hari Pahlawan kembali datang membawa kenangan tentang darah, air mata, dan semangat pengorbanan yang tak ternilai. Di berbagai penjuru negeri, upacara digelar, tabur bunga dilakukan, dan bendera merah putih kembali berkibar dengan gagah. Namun di balik segala kemegahan peringatan itu, ada kegetiran yang perlahan menyesak di dada: nasionalisme kita hari ini terasa kehilangan arah, menjelma menjadi simbol tanpa jiwa, perayaan tanpa makna.
Para pahlawan yang gugur di Surabaya, di medan-medan perang lain di tanah air, bukanlah orang-orang yang hanya mengangkat senjata. Mereka adalah jiwa-jiwa yang berani menantang ketakutan demi sebuah keyakinan: bahwa bangsa ini harus berdiri di atas kejujuran, kehormatan, dan harga diri. Mereka menanggung lapar, luka, dan kehilangan demi memastikan generasi setelahnya bisa hidup dalam kemerdekaan. Tapi jika mereka bisa melihat keadaan bangsa kini, mungkin mereka akan menangis bukan karena nostalgia, melainkan karena kecewa.
Sebab bangsa yang mereka selamatkan kini justru terperangkap dalam penjajahan baru — bukan oleh bangsa lain, melainkan oleh diri sendiri. Kita dijajah oleh keserakahan, diperbudak oleh kekuasaan, dan dikuasai oleh hasrat untuk menang tanpa moral. Nilai kejujuran yang dulu menjadi senjata kini dianggap kelemahan. Integritas yang dulu menjadi kebanggaan kini justru dipinggirkan. Di banyak ruang publik, suara kebenaran tenggelam dalam hiruk pikuk kepentingan pribadi dan politik transaksional.
Nasionalisme yang dulu lahir dari semangat pengorbanan kini digantikan oleh mentalitas mencari keuntungan. Banyak yang berbicara tentang cinta tanah air, tetapi sedikit yang benar-benar mencintainya dengan tindakan nyata. Kita berteriak lantang soal bangsa, namun mudah tergoda menjual prinsip demi jabatan dan fasilitas. Kita bangga pada bendera, namun tak segan menodai maknanya dengan perilaku yang merusak nilai-nilai kebangsaan.
Korupsi yang merajalela, birokrasi yang kian menjauh dari rakyat, dan ketimpangan sosial yang semakin tajam — semuanya menjadi potret buram dari bangsa yang kehilangan arah moral. Dalam ruang-ruang kekuasaan, nurani sering kali kalah oleh hitung-hitungan politik. Sementara di kampung-kampung, rakyat kecil terus bergulat dengan kemiskinan yang seolah tak kunjung berakhir. Inilah wajah getir nasionalisme kita: di satu sisi dibungkus dengan retorika patriotisme, di sisi lain rapuh karena kehilangan kejujuran.
Hari Pahlawan seharusnya bukan sekadar upacara tahunan atau momentum nostalgia sejarah. Ia mestinya menjadi cermin besar untuk kita menatap wajah sendiri — apakah kita masih memiliki semangat juang yang sama seperti mereka yang gugur, atau justru menjadi pewaris nama tanpa makna. Sebab kemerdekaan yang diwariskan bukan sekadar kebebasan dari penjajahan fisik, tetapi juga kemerdekaan berpikir dan berperilaku bermoral. Sayangnya, banyak di antara kita yang justru memperlakukan kemerdekaan seperti lisensi untuk berbuat sekehendak hati.
Kita sering kali lupa bahwa nasionalisme bukan hanya soal mencintai negeri ini, tetapi juga berani mengoreksi dan memperbaikinya. Cinta sejati kepada tanah air justru tampak ketika kita mampu berkata “tidak” pada ketidakadilan, berani menolak kebohongan, dan bersedia berbuat meski tanpa tepuk tangan. Dalam situasi seperti hari ini, menjadi jujur adalah bentuk keberanian paling tinggi, dan memperjuangkan kebenaran adalah tindakan kepahlawanan paling nyata.
Jika dulu para pahlawan bertempur dengan senjata, kini pertempuran kita adalah melawan kemunafikan, kebodohan, dan ketidakpedulian. Pertempuran itu berlangsung setiap hari — di ruang birokrasi, di dunia pendidikan, di media sosial, bahkan dalam hati kita sendiri. Kita sedang diuji: apakah mampu menjaga api nasionalisme tetap menyala, atau membiarkannya padam di tengah gemerlap dunia yang serba cepat dan dangkal.
Di tengah kegetiran ini, masih ada harapan. Masih ada anak muda yang bekerja tanpa pamrih, guru yang mengajar di pelosok dengan cinta, petani yang menanam tanpa menyerah, dan warga yang saling menolong tanpa pamrih. Mereka adalah pahlawan tanpa nama, penjaga moral bangsa di tengah zaman yang kian kehilangan arah. Dari merekalah kita belajar, bahwa nasionalisme sejati tidak memerlukan panggung dan sorotan, cukup keikhlasan untuk berbuat bagi sesama.
Hari Pahlawan kali ini seharusnya menggugah kita semua: bahwa tugas generasi hari ini bukan hanya mengenang, tetapi melanjutkan. Bukan hanya menaruh bunga di makam, tapi menanam nilai-nilai kejujuran dan pengabdian dalam kehidupan. Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang pandai bercerita tentang masa lalunya, tetapi bangsa yang mampu menjaga semangat masa lalu itu tetap hidup di masa kini.
Nasionalisme memang terasa getir hari ini. Tapi mungkin, dari rasa getir itulah kita kembali belajar untuk menghargai makna perjuangan. Bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan tanggung jawab. Dan bahwa pahlawan sejati bukan hanya mereka yang gugur, melainkan juga mereka yang tetap berdiri teguh di tengah kerusakan moral — demi memastikan bangsa ini tidak kehilangan arah dan nuraninya. (*)