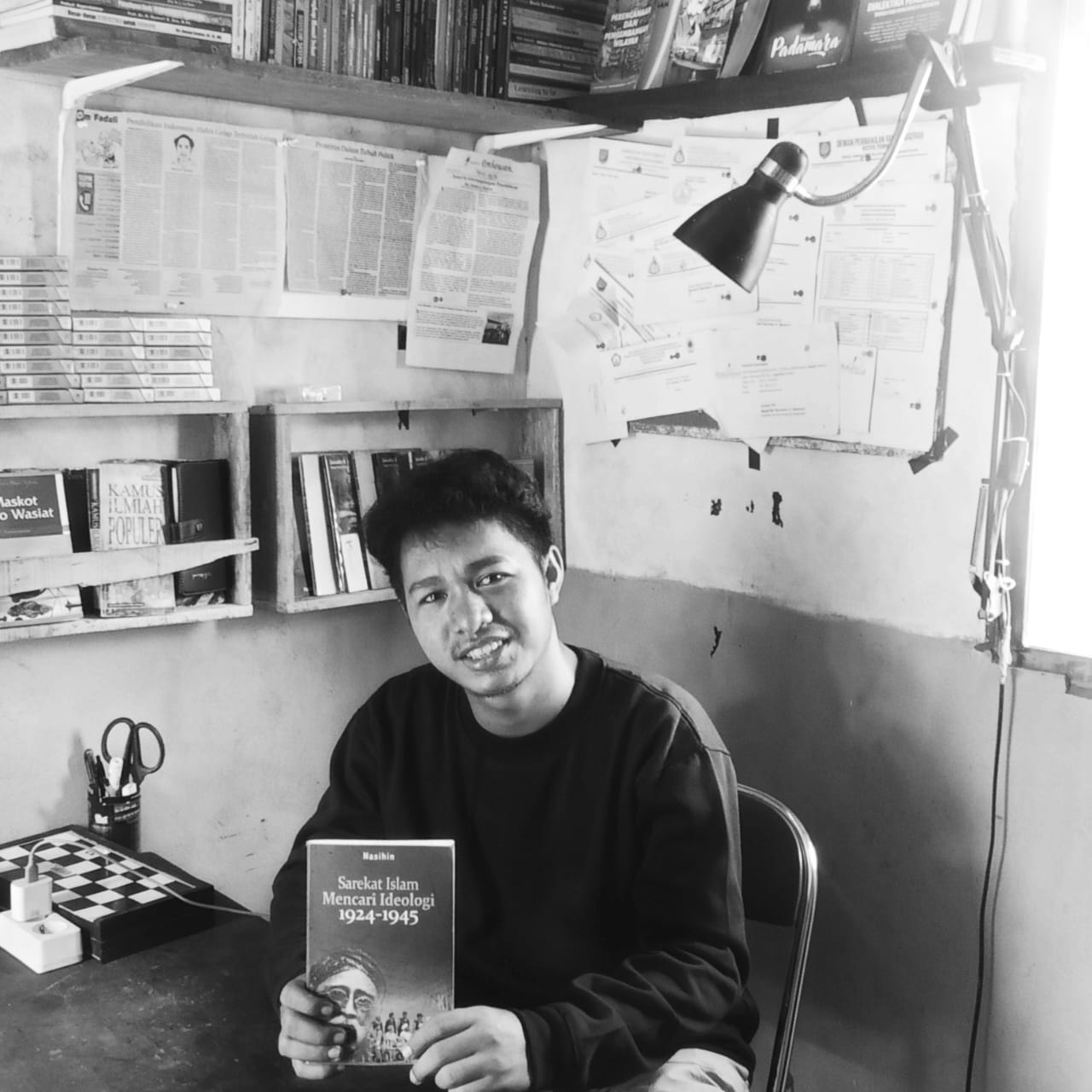Oleh: Bachtiar S. Malawat
Forum Insan Cendekia Ternate
___________________________
TERNATE selalu diceritakan sebagai kota sejarah, kota Islam, kota adat, kota rempah, dan segala label romantik lainnya. Tapi di balik cerita manis itu, kota ini sedang mengalami kejumudan kultural yang panjang. Kota ini bukan hanya kota dengan gunung aktif, tapi juga kota yang menyimpan letupan sosial, politik, dan budaya yang tak pernah benar-benar selesai.
Kita hidup dalam ilusi bahwa adat dan kebesaran sejarah cukup untuk menjaga jati diri. Padahal, kenyataannya, sebagian besar anak muda Ternate tak lagi mengenal sejarah lokal secara substansial. Mereka lebih hafal nama selebgram Jakarta daripada tokoh-tokoh pejuang dari Ternate. Bahkan nama-nama seperti Sultan Baabullah atau Jogugu Arif Bila hanya menjadi nama jalan, bukan spirit perjuangan.
Ironis, kota ini dihuni oleh masyarakat yang konon “beradat”, tapi pada praktiknya kita menjual adat dalam brosur pariwisata, bukan dalam praksis sosial. Di hadapan penguasa, adat tunduk. Di hadapan modal, budaya dijual murah. Maka yang tersisa hanyalah pertunjukan—bukan kesadaran.
Literasi di Ternate adalah proyek gagal. Bukan karena orang Ternate bodoh, tapi karena sistem sosial dan politik yang secara sistematis mematikan daya pikir kritis. Sekolah-sekolah hanya menjadi tempat reproduksi pengetahuan hafalan. Guru lebih sibuk urus administrasi BOS daripada mendiskusikan sejarah perlawanan Ternate terhadap kolonial.
Perpustakaan di Ternate sepi. Buku-buku lokal tenggelam dalam pujian palsu dan seminar tak bermutu. Bahkan lembaga adat sekalipun, tak mampu lagi menjadi pusat transmisi pengetahuan. Mereka lebih suka menjadi bagian dari birokrasi kekuasaan ketimbang menjadi oposisi budaya.
Padahal dalam sejarahnya, Ternate adalah pusat intelektual. Manuskrip Arab-Melayu, naskah-naskah kesultanan, dan tradisi lisan memperlihatkan kedalaman literasi yang luar biasa. Tapi hari ini? Naskah itu tersimpan di museum, tak tersentuh. Generasi muda bahkan tidak bisa membaca aksara Ternate. Mereka hidup tanpa akar.
Pertanyaannya, siapa yang memutus rantai literasi ini? Jawabannya jelas, kekuasaan. Sejak zaman kolonial hingga pascareformasi, penguasa selalu takut pada masyarakat yang cerdas. Maka buku dibatasi, diskusi dicurigai, dan sekolah dijadikan alat domestikasi. Literasi bukan lagi alat pembebasan, tapi alat pelanggengan sistem.
Di Ternate, politik adalah panggung sirkus identitas. Nama marga, garis keturunan, atau afiliasi adat seringkali dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Tapi jangan salah paham, ini bukan politik berbasis nilai-nilai leluhur, melainkan manipulasi simbolik untuk mengamankan kursi dan proyek.
Para elit lokal bicara soal “kearifan lokal”, tapi tak pernah sungguh-sungguh membela rakyat kecil. Mereka rajin hadir di ritual adat, tapi absen dalam kebijakan pro-rakyat. Bahkan Kesultanan sendiri, yang seharusnya menjadi benteng kultural, kerap dijadikan alat legitimasi politik oleh penguasa dan calon legislatif.
Lebih parah, anak-anak muda yang masuk dunia politik justru terjebak dalam euforia kekuasaan, bukan idealisme. Mereka tidak masuk untuk menggugat struktur yang korup, tapi untuk ikut mencicipi. Maka lahirlah generasi politisi muda yang malas baca, malas riset, tapi rajin posting kampanye dan lobi anggaran.
Di sinilah tragedi kita, kekuasaan tak lagi soal pengabdian, tapi soal jatah. Siapa dekat dengan penguasa, dia dapat proyek. Siapa vokal, dia dibungkam. Siapa kritis, dia dikucilkan. Maka muncul budaya diam budaya “tra mau cari musuh” yang sebenarnya hanya bentuk baru dari ketakutan struktural.
Budaya lokal Ternate kaya, tapi ia juga mengandung paradoks, di satu sisi menjadi alat identitas, di sisi lain membekukan transformasi sosial. Banyak praktik sosial yang bertahan bukan karena relevan, tapi karena takut dinilai “melawan adat”.
Padahal adat bukan hukum Tuhan yang statis. Adat itu hidup, dinamis, dan bisa direvisi. Tapi ketika kritik terhadap adat dianggap penghinaan, maka di situlah kultur berubah menjadi tirani. Masyarakat tidak diberi ruang untuk berpikir ulang tentang relevansi nilai-nilai lama terhadap dunia modern.
Contoh nyata, patriarki dalam rumah tangga, otoritarianisme dalam struktur adat, serta absennya ruang bagi perempuan untuk memimpin secara sah dalam struktur kultural. Semua itu dibungkus atas nama “tradisi”, padahal sesungguhnya itu adalah bentuk hegemoni lama yang tak mau ditantang.
Hal yang sama terjadi di dunia pendidikan dan agama. Anak muda tidak diberi ruang bertanya. Ulama dianggap tidak boleh dibantah. Guru adalah pemilik kebenaran tunggal. Maka lahirlah generasi penurut, bukan generasi pembaru. Ini penyakit struktural yang harus dikritik dengan tajam dan radikal.
Pertanyaannya kini adalah, mau dibawa ke mana Ternate? Apakah kita akan terus tenggelam dalam glorifikasi masa lalu dan terus hidup dalam bayang-bayang struktur kultural yang membungkam? Atau kita mulai membangun revolusi kultural yang dimulai dari kesadaran baru.
Ternate butuh gerakan intelektual. Bukan gerakan yang sibuk dengan seminar dan baliho, tapi gerakan akar rumput yang menyentuh rumah, sekolah, masjid, dan pasar. Kita butuh literasi kritis di setiap sudut kota. Kita butuh anak muda yang berani bicara, menulis, menggugat, dan membangun narasi baru.
Ternate juga butuh keberanian mereformasi struktur adat. Kesultanan tidak boleh hanya menjadi pelengkap seremoni. Ia harus menjadi pusat kritik budaya, bukan alat legitimasi kekuasaan. Lembaga adat harus merefleksikan ulang relasi mereka dengan rakyat, bukan hanya menjaga simbol kosong.
Dan yang paling penting, kita butuh membangun kesadaran sejarah yang hidup. Bukan hanya hafalan nama-nama Sultan, tapi pemahaman akan perjuangan melawan kolonial, strategi diplomasi, nilai-nilai perlawanan, dan prinsip kedaulatan. Sejarah harus jadi sumber daya mental untuk melawan kemiskinan intelektual. Akhir Kata, Muslim Cendikia Pemimpin. (*)